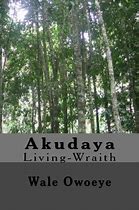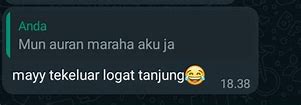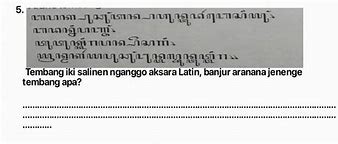Cerpen berjudul Gara-Gara Nenek Lupa
Setiap akhir tahun, sekolah Rino libur. Di saat itu, Rino, Ayah, dan Ibu akan naik ke mobil dan berkunjung ke rumah Nenek Ida di desa. Nenek Ida mempunyai ladang. Rino suka sekali berlibur ke desa Nek Ida.
Setiap pertengahan tahun, sekolah Rino juga libur. Namun di saat itu, giliran Nek Ida yang berkunjung ke rumah Rino. Begitulah cara keluarga Rino mengatur liburan. Agar tidak bosan, kadang mereka liburan di kota, kadang di desa pertanian.
Akan tetapi, di tahun ini, Nenek Ida membuat kesalahan.
“Aku yakin, saat ini, giliranku untuk liburan ke kota,” gumam Nek Ida yang mulai pelupa. Pelan-pelan, ia lalu mengemasi baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam koper.
Pada saat yang sama, ibu Rino juga sedang mengemasi tas. Ibu tampak tidak bersemangat. Sambil menutup tasnya, ibu Rino berkata,
“Ibu sebetulnya ingin sekali bisa liburan ke pantai. Sekaliii saja supaya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.”
Rino dan adiknya langsung berseru setuju.
“Aku juga ingin ke pantai, Bu! Jangan ke rumah Nek Ida terus atau cuma berkeliling kota ini. Bosan. Kalau liburan ke laut, kita kan bisa berenang dan menggali pasir. Yah, Ayah, tahun ini kita liburan ke pantai, saja ya?” seru Rino bersemangat.
“Tentu saja tidak bisa, sayang,” kata ayah Rino. “Akhir tahun ini, kita akan mengunjungi Nenek seperti biasa. Jangan sampai Nenek kecewa dan bertanya-tanya kalau kita tidak datang. Tahun depan saja kalau mau ke pantai. Supaya Nenek juga sudah diberitahu jauh-jauh hari.”
Rino jadi lesu. Namun, kata-kata ayahnya ada benarnya. Nek Ida pasti sedih kalau mereka tidak datang ke pertaniannya. Rino tak ingin membuat neneknya yang baik hati itu jadi sedih.
Keesokan harinya, cuaca sangat cerah. Rino, Ayah dan Ibu naik ke mobil. Tak lama kemudian, mereka sudah ada dalam perjalanan menuju peternakan Nek Ida.
Di sepanjang jalan yang agak macet dan panas, Rino masih berharap andai mereka bisa berlibur ke pantai. Karena ayah Rino mulai kehausan, ia menepikan mobil di dekat kafe pinggir jalan.
Mereka bertiga turun dari mobil. Tiba-tiba, wajah ibu Rino tampak kaget, gembira dan dengan bersemangat menunjuk ke parkiran.
“Lihat! Mobil itu mirip mobil Nenek!”
Rino dan ayah menengok. Mereka bertiga lalu melangkah pelan mendekati mobil itu. Astaga, itu memang mobil Nek Ida. Nenek bersandar di pintu mobil dan sedang menyeruput jus jeruk.
Seketika itu juga, Rino berlari dan memeluk neneknya. Ayah dan Ibu juga memeluk Nenek dan bertanya heran.
“Ibu mau ke mana?” tanya Ayah.
“Tentu saja mau ke rumah kalian!” kata Nek Ida heran. Namun ia lalu menyadari kesalahannya. “Astaga, harusnya, ini giliran kalian berlibur di pertanian, ya?” serunya.
Ibu Rino tersenyum cerah.
“Tidak apa, Bu! Sekarang, kita buat rencana baru saja. Bagaimana kalau tahun ini kita bikin perubahan. Ibu mau kalau kita berlibur ke pantai?” tanya ibu Rino penuh harap.
Wah, tak disangka, wajah Nek Ida berubah sangat ceria.
“Tentu saja Nenek mau! Nenek mau bermain air laut!” kata Nek Ida penuh semangat.
“Yeeeeeey… Nanti aku temani Nenek main air!” teriak Rino tak kalah girang.
Rino, Ayah dan Ibu tertawa geli melihat Nenek dan cucunya yang bersemangat. Kini, ayah Rino sibuk melihat peta jalannya.
“Hmmm! Sekarang ini, kita hanya berjarak sembilan mil dari pantai. Jadi, ayo kita ke sana sekarang!” ajak ayah Rino.
Di mobil, Nek Ida tertawa dan berkata,
“Liburan kita mungkin sudah mulai membosankan dan tercampur aduk. Makanya Nenek sampai lupa harus tetap di pertanian atau mengunjungi kalian! Syukurlah, Nenek membuat sedikit kesalahan!”
“Semua orang pernah berbuat kesalahan, Nek. Tapi, kesalahan Nenek ini sungguh menyenangkan!” kata Rino.
Mereka semua tertawa lagi. Dan ketika udara pantai yang asin mulai tercium, hati mereka semakin gembira.
Cerpen berjudul Obat Bosan dari Nenek
Obat Bosan dari Nenek
Ayah dan Ibu belum pulang dari kantor. Mbak Asti dan Mas Pur pergi kuliah. Kawan bermain Lili, Oni sedang sakit kuning. Vita, tetangga sebelah sedang pergi ke rumah saudaranya. Nah, tinggal Lili dan Mbok Nah yang ada di rumah. Mbok Nah sibuk menyetrika.
Lili merasa kesal dan bosan. PR sudah selesai. Dia tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Biasanya dia bisa bermain dengan Vita atau Oni.
“Sudah, tidur saja Li!” usul Mbok Nah.
“Ah, orang tidak mengantuk disuruh tidur!” Lili menggerutu. “Atau main ke rumah Dede? Biar Mbok antarkan!” Mbok Nah menawarkan.
“Malas ah, rumahnya jauh. Biasanya jam empat begini dia belum bangun. Dia ‘kan harus tidur siang setiap hari!” Lili menolak. Tiba-tiba Lili mendapat gagasan. Dia pergi ke kamar Ibu dan menelepon Nenek.
Sesudah bercakap-cakap sejenak, Lili mulai mengeluh, “Nek, kalau tiap hari begini Lili bisa mati. Bosannya setengah mati. Vita pergi, Oni sakit. Di rumah tak ada siapa-siapa!” “Wah, wah, jangan sebut-sebut mati. Bosan itu ‘kan penyakit yang paling gampang diobati. Sudah setua ini Nenek tak pernah merasa bosan!”
“Tentu saja. Cucu-cucu yang tinggal sama Nenek segudang. Di sana ‘kan selalu ramai. Di sini sepi!”
“Selalu sepi tidak enak, selalu ramai juga tidak enak. Nah, begini saja. Kamu sabar sebentar. Nenek akan segera datang membawakan obat untuk penyakit bosanmu!”
“Baiklah, cepat datang, ya Nek!” kata Lili dengan gembira dan meletakkan gagang telepon. Dalam hati Lili bertanya-tanya seperti apa kiranya obat bosan itu.
Kalau berbentuk pil, wah, lebih baik tidak usah saja. Kalau berbentuk permainan, nah ini lebih asyik. Tetapi, mainan pun lama-lama bias membosankan.
Sambil menunggu Nenek datang, Lili mendekati Mbok Nah lagi. “Mbok, Mbok, Nenek mau datang membawakan obat bosan. Tahu tidak Mbok, obat bosan itu seperti apa sih?” Mbok Nah tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepala.
“Lili, Lili, mana ada sih obat bosan? Ada juga obat batuk, obat sakit perut, obat flu. Kalau Mbok Nah bosan, obatnya sih gampang saja. Stel saja kaset dangdut. Hilang sudah rasa bosannya!” kata Mbok Nah.
Sekarang Lili yang tertawa. “Kalau saya sih tambah bosan mendengar kaset lagu dangdut. Kaset lagu anak-anak saja, paling seminggu enak didengar. Sesudah itu bosan saya mendengarnya!” kata Lili.
“Ya, sudah. Kesukaan orang ‘kan Iain-Iain. Kita lihat saja nanti, Nenek bawa obat bosan yang bagaimana!” kata Mbok Nah. Empat puluh menit kemudian Nenek datang. Lili menyambutnya dengan gembira. Nenek mengeluarkan beberapa buah buku dari tasnya.
“Yaaa, obat bosannya bukuuuu. Lili kan malas baca buku!” seru Lili dengan kecewa.
“Hei, kamu belum tahu nikmatnya membaca buku rupanya. Kalau sudah senang membaca, kamu tidak akan pernah merasa bosan lagi. Nah, sekarang coba kamu baca buku yang ini!” kata Nenek sambil memberikan sebuah buku cerita bergambar.
“Kalau tebal, malas ah bacanya!” kata Lili dengan segan. “Tidak, ini cuma 24 halaman. Tiap halaman ada gambarnya dan teksnya sedikit. Ceritanya tentang beruang kecil. Bagus, Iho! Anak-anak di berbagai negara sudah membaca buku ini!” Nenek memberi semangat.
Lili mulai membaca. Eh, ternyata menarik juga. Nenek tersenyum dan berkata, “Kamu sudah kelas empat. Sayang sekali kamu belum mengenal banyak cerita yang bagus. Sebetulnya buku bukan hanya buku cerita, tetapi ada juga buku tentang berbagai pengetahuan. Misalnya kamu mau tahu asal minyak tanah, atau cara kerja tukang pos, atau tentang menanam bunga atau apa saja, semua ada bukunya!”
“lya, Nek? Kalau buku cara membuat mainan dari kertas, ada tidak Nek? Itu Iho, seperti membuat perahu, burung. Lili mau baca buku itu kalau ada!” kata Lili.
“Tentu saja ada. Nanti, kita bisa cari di toko buku. Nenek akan tunjukkan berbagai macam buku. Sekarang, kamu bisa membaca buku-buku yang tipis ini dulu. Nanti, makin lama kamu akan terbiasa dan senang membaca buku cerita yang lebih tebal. Kalau kamu suka membaca, kamu tak akan merasa bosan. Bermain dengan kawan memang suatu hal yang baik, tetapi kebiasaan membaca juga perlu dipupuk. Nanti kalau kamu menjadi mahasiswi, kamu sudah terbiasa membaca buku pelajaran yang tebal-tebal!” kata Nenek.
“Buku ceritanya dari mana, Nek?” tanya Lili.
“Nanti Nenek belikan beberapa. Lalu setiap bulan Ibu bisa membelikan satu atau dua buah buku. Kemudian kamu bisa tukar pinjam dengan kawan-kawanmu yang punya buku cerita. Selain itu kamu juga bisa pinjam dari perpustakaan sekolah. Di sekolahmu ada perpustakaan tidak?” tanya Nenek.
“Ada. Tapi Lili belum pernah pinjam!” Lili mengaku terus terang.
“Lili! Lili! Seharusnya, perpustakaan sekolah dimanfaatkan. Tetapi, baiklah! Sekarang Nenek akan membimbingmu. Nenek akan pinjamkan buku-buku yang menarik, supaya kamu rajin membaca. Sesudah itu berangsur-angsur kamu mulai membaca buku yang banyak teksnya!” kafa Nenek.
Selama satu bulan Nenek akan sering datang membawa buku cerita untuk Lili. Sampai akhirnya, bila Lili sudah gemar membaca, Nenek tak perlu lagi membawakan buku-buku cerita.
Lili sudah bisa mencari sendiri buku cerita atau pengetahuan yang dibacanya. Yang penting juga, Lili sudah mendapat obat bosan yang ampuh dari Nenek, hingga seumur hidup dia akan bebas dari penyakit bosan.
Baca Juga: Apa Saja Unsur-Unsur Ekstrinsik Cerpen? | Bahasa Indonesia Kelas 9
Broken home, judul kali ini adalah broken home. Siapa sih yang gak tau apa itu broken home, semua orang pasti tau, kebanyakan dari mereka mengira itu hanya masalah sepele, tapi bagi mereka yang merasakan, itu adalah pengalaman terburuk di kehidupan mereka.
Aku, adalah bukti nyata kalau broken home sangat menyeramkan. Bayangkan saja, di masa aku kecil aku kehilangan sosok ibu, sosok yang sangat kuat bagi seorang anak kecil. Banyak yang mengira kalau aku baik-baik saja, ada juga yang mengira kalau aku tidak terpengaruh oleh adanya kerusakan rumah di kala aku kecil.
Semua itu bohong, sewaktu kecil hampir setiap hari aku menangis, hampir setiap kali rasanya Hampa. Kosong. Sunyi. Sepi. Sedih. Apa yang mereka lihat itu hanya alter ego. Kepribadian yang lain dari diriku yang asli atau bisa dikatakan itu adalah sisi lain dari diriku.
Terlalu lama kayaknya prolognya. Tanpa basa-basi lagi, namaku Toto, mungkin sekarang aku lebih baik daripada aku yang dulu. Sudah lama sekali aku tidak menangis, dan sudah lama juga aku tidak merasakan kasih sayang ibu. Ayah dan ibuku bercerai ketika umurku 4 tahun, masih sangat kecil, bahkan terlalu kecil bagi seorang anak yang harus ditinggalkan ibunya.
Aku masih ingat semua kejadian awal, semua pertengkaran ayah dan ibuku. Semua kejadian di pengadilan, semuanya terekam baik di kepalaku, di otakku, memori itu seakan tidak bisa dihapus. Termasuk kata terakhir ibuku sebelum dia pergi meninggalkanku, ‘Mulai sekarang jadi anak yang baik, jangan nyusahin ayah. Ibu pergi dulu.’ Dengan polosnya aku menjawab, ‘Iya, ibu cepat pulang’. Jawaban yang terlalu lugu, aku masih umur 4 tahun dan aku hanya berharap bisa ketemu ‘dia’ lagi. Ketika itu aku masih berpikir mungkin ibuku pergi ke luar kota, lalu tiba-tiba pulang bawa mainan besar, tapi kenyataannya tidak. Itu tidak pernah terjadi. Entah bagaimana aku tahu kalau sebenarnya ibuku tidak pergi, melainkan dia bercerai dengan ayahku. Coba pikirkan apa yang aku bayangkan? Yang saat itu bayangkan adalah kosong. Aku bingung apa itu cerai?.
Ada pertanyaan yang sampai saat ini menjadi misteri di kepalaku. Pernyataannya sederhana, ‘Kenapa kalian cerai? Apa karena kehadiranku? Atau justru ada penyebab lain?’. Ingin sekali aku bertanya kepada ayahku, tapi buat apa juga, biarlah itu jadi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu.
Setelah perceraian itu, aku, ayahku, neneku, tanteku, dan kedua saudaraku pindah. Aku tumbuh sebagai anak yang tidak pernah merasakan sosok ibu. Bahkan ketika pendaftaran masuk ke sekolah dasar aku hanya ditemani tanteku. Tumbuh sebagai anak yang kurang perhatian, membuatku dipaksa menjadi dewasa. Ada yang bilang ketika kita bertambah umur, maka kita akan bertambah dewasa. Tapi itu tidak berlaku untukku, menurutku keadaanlah yang membuat kita bertambah dewasa, umur hanya sebuah angka.
Ketika aku kelas 2 sd salah satu temanku berkata dia lagi kesal sama ibunya, dia bilang begini, ‘Aku malas sama ibuku’. Lalu aku menjawab, ‘Kenapa?’. Dia menjawab, ‘Kenapa aku masih ditunggu di depan pintu gerbang sekolah? Kan aku malu’ Aku diam, bingung. ‘Kenapa malu?’ jawabku polos. ‘Malu aja’ jawab dia, singkat. Entah apa yang ada dipikiran dia, memang ada anak yang malu kalau masih ditunggu orangtuanya?.
Tumbuh sebagai anak yang kurang kasih sayang. Ketika kecil aku melihat cinta dan jenisnya seperti seram, ketika remaja aku takut itu masih kugenggam nyaman, dan semua itu aku dapat dari kecil.
Ketika kelas 3 sd, ayahku menikah lagi. Aku bahagia, entah apa yang membuat aku bahagia. Aku tumbuh di lingkungan yang berbeda, kehidupanku bisa dibilang nomaden. Sewaktu kecil aku tinggal bersama kedua orangtuaku, tak lama dari itu kami berpisah aku ikut ayahku, dan ibuku pergi. Setelah itu juga aku dikasih sebuah kehidupan baru yaitu sekolah. Kelas 4 sd aku berpindah sekolah, yang mana itu memaksa otakku, tubuhku, kedewasaanku. Aku bilang dari awal, bahwa lingkunganlah yang membuat kita dewasa, umur hanyalah angka.
Di sekolah yang baru aku dipaksa adaptasi, aku dipaksa menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Teman pertamaku di sd yang baru pernah bercerita tentang ibunya, dia bilang, ‘Kamu pernah gak dimarahi?.’ ‘Maksutnya?’ tanyaku. ‘Iya gitu, kayak misal kita berbuat nakal terus dimarahi, pernah gak?’ jawab dia. ‘Engga deh, gak pernah’ jawabku, singkat. Memang aku tidak pernah berbuat nakal kalau di depan ayahku, tapi mungkin pernah sih kalau tidak ada ayahku. Ayahku mendidik aku cukup keras, jadi aku selalu takut ayahku.
Ada yang pernah bilang juga sama aku, dia bilang gini, ‘Kamu pernah gak tidur bareng orangtua?.’ Aku jawab jujur, ‘Pernah, tapi itu dulu’ Dia menjawab, ‘Enak ya, coba aja aku jadi kamu’ ‘Yakin mau jadi kayak aku?’ tanyaku. ‘Iyalah, enak jadi kamu,’ jawab dia. ‘Coba bayangin aku, aku nih, yang udah besar masih aja tidur sekamar bareng ayah-ibuku.’ ‘Bersyukur aja kali, lah coba, kamu masih mending, aku?’ sahutku. ‘Udah lama gak tidur bareng, kedua orangtuaku cerai sedari aku kecil’ ‘Yang bener?’ tanya dia, kaget. ‘Iyaalah, masa aku bohong’ kataku.
Lanjut ke masa smp, dimana lagi-lagi aku harus bertemu orang baru, bagiku pengalaman ini tidak cukup asing. Aku selalu ngelakuin ini dari kecil. Ketika kelas 3 smp, salah temanku bertanya, ‘Gimana sih rasanya broken home?’ Aku menjawab, ‘Ya gitu, enak sih kalau dipikir’ Temanku bingung, aku juga bingung. ‘Kok enak? Apanya yang enak?’ ‘Gatau, asal keluar di kepala aja’ jawabku. ‘Tapi jujur, broken home membuatku semakin dewasa, aku jadi tau kalau tidak semua cinta itu baik, tapi sebagian dari cinta itu seram’ sambungku.
Dari kecil aku dibentuk oleh rasa takut, hanya ada satu pertanyaan yang selalu aku ingat ketika aku lagi sendiri, ‘Untuk apa aku dilahirkan, kalau pada akhirnya aku ditinggalkan.’ Tumbuh tanpa kasih sayang membuat aku menjadi pendiam, aku sering kehilangan emosi. Aku lebih senang ketika melihat kejadian brutal, apa aku tumbuh menjadi psikopat?. Tidak, aku bukan psikopat, tapi aku hanya orang yang kehilangan emosinya. Karena aku, kehilangan segalanya.
Keluargaku meninggal 2 minggu yang lalu, para polisi mengatakan kalau mereka dibunuh oleh seseorang. Dan lebih kejamnya pembunuhan ini direncana, seakan pembunuh ini punya dendam terhadap keluargaku.
‘Udah selesai ceritanya?’ kata temanku. Ada keheningan sesaat.
‘Berikan ini kepada keluargaku, bilang ke mereka aku sudah bahagia’ kataku. ‘Ini apa?’ tanya dia. ‘Cuma secarik kertas yang isinya mungkin bisa membuat mereka tenang’ kataku. Dia mengambil secarik kertas, lalu memasukkan ke katong yang ada di dadanya. ‘Pasti aku sampaikan’ katanya. ‘Kamu sudah siap? Kalau sudah, ayo kita pergi’ ‘Aku selalu siap, aku tau konsekuensinya. Aku tau apa yang kuperbuat’ kataku.
Kami berdua jalan di sebuah lorong, gelap, pengap, tidak ada jendela sekalipun selama kami berdua berjalan. Kalau kalian tidak tau, temanku bekerja di kepolisian. 3 menit kami berjalan, dengan keadaan tanganku terikat borgol. Pada akhirnya kami sampai di depan khalayak orang, hakim, serta puluhan polisi.
Aku berdiri di depan mereka semua, dengan tiang setinggi 4 meter di sebelahku. ‘Suadara Toto, anda dinyatakan bersalah, atas pembunuhan berantai yang menyebabkan 13 orang meninggal. Dan tragisnya anda melakukan itu dalam waktu 3 bulan dan 13 orang itu juga termasuk keluarga anda. Maka sesuai hukum yang berlaku anda akan digantung. Apa anda siap menanggung itu semua?’ kata hakim. ‘Saya selalu siap’ jawabku, singkat. ‘Apa ada kata terakhir?’ tanya hakim. ‘Mana yang lebih buruk? Hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik?.’
Cerpen Karangan: Basyasah Blog / Facebook: Syahvier
Cerpen Broken Home merupakan cerita pendek karangan Basyasah, kamu dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen cerpen terbaru buatannya.
"Kamu suka cerpen ini?, Share donk ke temanmu!"
Cerpen berjudul Robohnya Surau Kami
Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi.
Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya Kakek.
Sebagai penjaga surau, Kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali se-Jumat. Sekali enam bulan ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum.
Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar, sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari.
Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi.
Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya.
Sekali hari aku datang pula mengupah Kakek. Biasanya Kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini Kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki Kakek. Tidak pernah aku melihat Kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya Kakek, “Pisau siapa, Kek?”
Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia. Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak.
Tiba-tiba aku ingat lagi pada Kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang Kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan Kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya Kakek lagi. “Apa ceritanya, Kek?”
“Kurang ajar dia,” Kakek menjawab.
“Mudah-mudahan pisau cukur ini, yang kuasah tajam-tajam ini, menggorok tenggorokannya.”
“Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepada-Nya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal.”
Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan Kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi Kakek, “Bagaimana katanya, Kek?”
Tapi Kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku, “Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku?”
Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu, kalau Kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku biarkan Kakek dengan pertanyaannya sendiri.
“Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain, tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wataala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepada-Nya? Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan Pengasih dan Penyayang kepada umat-Nya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi. Aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepada-Nya. Aku sembahyang setiap waktu. Aku puji-puji Dia. Aku baca Kitab-Nya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk.”
Ketika Kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku, “Ia katakan Kakek begitu, Kek?”
“Ia tak mengatakan aku terkutuk. Tapi begitulah kira-kiranya.”
Dan aku melihat mata Kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati Kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya Kakek bercerita lagi.
Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di samping-Nya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang- orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan ‘selamat ketemu nanti’. Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya. Susut di muka, bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifat-Nya.
Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama.
‘Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku.’
‘Aku tidak tanya nama. Nama bagiku, tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia.’
‘Apa kerjamu di dunia?’
‘Aku menyembah Engkau selalu, Tuhanku.’
‘Setiap hari, setiap malam. Bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut nama-Mu.’
‘Ya, Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembah-Mu, menyebut-nyebut nama-Mu. Bahkan dalam kasih-Mu, ketika aku sakit, nama-Mu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hati-Mu untuk menginsafkan umat-Mu.’
Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf, pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja, tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu.
‘Lain lagi?’ tanya Tuhan.
‘Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, O, Tuhan yang Mahabesar, lagi Pengasih dan Penyayang, Adil dan Mahatahu.’ Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya.
Tapi Tuhan bertanya lagi: ‘Tak ada lagi?’
O, o, ooo, anu Tuhanku. Aku selalu membaca Kitab-Mu.’
‘Sudah kuceritakan semuanya, O, Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah Mahatahu.’
‘Sungguh tidak ada lagi yang kaukerjakan di dunia selain yang kauceritakan tadi?’
‘Ya, itulah semuanya, Tuhanku.’
Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap.
Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai empat belas kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun, tak mengerti juga.
‘Bagaimana Tuhan kita ini?’ kata Haji Saleh kemudian, ‘Bukankah kita di suruh-Nya taat beribadat, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan-Nya ke neraka.’
‘Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadat,’ kata salah seorang di antaranya.
‘Ini sungguh tidak adil.’
‘Memang tidak adil,’ kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
‘Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita.’
‘Kita harus mengingatkan Tuhan, kalau-kalau Ia silap memasukkan kita ke neraka ini.’
‘Benar. Benar. Benar.’ Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh.
‘Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapan-Nya, bagaimana?’ suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu.
‘Kita protes. Kita resolusikan,’ kata Haji Saleh.
‘Apa kita revolusikan juga?’ tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner.
‘Itu tergantung kepada keadaan,’ kata Haji Saleh. ‘Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan.’
‘Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh,’ sebuah suara menyela.
‘Setuju. Setuju. Setuju.’ Mereka bersorak beramai-ramai.
Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan.
Dan Tuhan bertanya, ‘Kalian mau apa?’
Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya: ‘O, Tuhan kami yang Mahabesar. Kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Mahakuasa setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini, atas nama orang-orang yang cinta pada-Mu, kami menuntut agar hukuman yang Kaujatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam Kitab-Mu.’
‘Kalian di dunia tinggal di mana?’ tanya Tuhan.
‘Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku.’
‘O, di negeri yang tanahnya subur itu?’
‘Ya, benarlah itu, Tuhanku.’
‘Tanahnya yang mahakaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan?’
‘Benar. Benar. Benar. Tuhan kami. Itulah negeri kami.’ Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang, bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu.
‘Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam?’
‘Benar. Benar. Benar. Itulah negeri kami.’
‘Di negeri, di mana penduduknya sendiri melarat?’
‘Ya. Ya. Ya. Itulah dia negeri kami.’
‘Negeri yang lama diperbudak negeri lain?’
‘Ya, Tuhanku. Sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku.’
‘Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya, dan diangkut ke negerinya, bukan?’
‘Benar, Tuhanku. Hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu.’
‘Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan?’
‘Benar, Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau.’
‘Engkau rela tetap melarat, bukan?’
‘Benar. Kami rela sekali, Tuhanku.’
‘Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan?’
‘Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala.’
‘Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan?’
‘Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kaubiarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja. Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai, Malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya!’
Semua menjadi pucat pasi tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu.
‘Salahkah menurut pendapatmu, kalau kami, menyembah Tuhan di dunia?’ tanya Haji Saleh.
‘Tidak. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun.’
Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari Kakek. Cerita yang memurungkan Kakek.
Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata apa aku tak pergi menjenguk.
“Siapa yang meninggal?” tanyaku kaget.
“Ya. Tadi subuh Kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur.”
“Astaga! Ajo Sidi punya gara-gara,” kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang.
Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya. Tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia.
“Ia sudah pergi,” jawab istri Ajo Sidi.
“Tidak ia tahu Kakek meninggal?”
“Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat Kakek tujuh lapis.”
“Dan sekarang,” tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab, “dan sekarang ke mana dia?”
“Kerja?” tanyaku mengulangi hampa.
“Ya, dia pergi kerja.” ***
" Baca Juga Cerpen Lainnya! "
"Kalau iya... jangan lupa buat mengirim cerpen cerpen hasil karyamu ke kita ya!, melalui halaman yang sudah kita sediakan
. Puluhan ribu penulis cerpen dari seluruh Indonesia sudah ikut meramaikan cerpenmu.com loh, bagaimana dengan kamu?"
Oleh: Dr. Mampuono, M.Kom. (Strategi Tali Bambuapus Giri)
#Seri kisah masa kecil
Saat-saat menjelang musim penghujan adalah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Orang di kampungku, Widuri, menyebut saat itu sebagai mangsa labuh. Hujan deras pertama di mangsa labuh yang mengguyur sawah dan ladang menyebabkan tanah-tanah keras dan bercelah ketika musim kering menjadi gembur. Apalagi jika tanah-tanah itu sudah dicangkul, ditebari biji, dicebloki bonggol, disiram, dirawat, dan disiangi, semua sumber makanan selama setahun akan segera muncul dari bumi. Padi, jagung, ketela, terung, tomat, cabai, deleg, gambas, waluh, bistru, semangka, dan kacang-kacangan adalah hasil bumi Widuri.
Di tahun 1978 ini penduduk kampung Widuri hampir semuanya bermata pencaharian sebagai petani. Ada sebagian yang menjadi pegawai negeri, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Mereka hanya tiga orang, yaitu Lik Kasroh, Lik Kasrun, dan Lik Sadimin. Jadi, wajar jika hujan pertama adalah anugerah terindah paling dinanti.
Hujan adalah pertanda kesuburan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan yang maha mengatur dalam hal ini. Mungkin kita bisa mencangkul tanah dan menyirami terus-menerus, tetapi kesuburan yang dimunculkan tidak akan seperti apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hujan-hujan pertama di mangsa labuh itu ajaib! Air dari langit itu seperti membawa mantra sakti yang akan menghidupkan kembali apa-apa yang sudah mati.
Kami biasanya menyambut mangsa labuh dengan menanam jagung. Tanah-tanah ladang yang beberapa minggu sebelumnya sudah dicangkul dan dikoak segera ditanami. Dikoak artinya pada jarak jarak tertentu tanah dicangkul dengan kedalaman sekitar 20 cm. Begitu hujan deras pertama tiba, paginya semua berduyun-duyun pergi ke ladang.
“Mpu, kamu bawa ceblok ya. Kamu ambil di pojok, semende di dekat pawon. Kamu ambil juga boding yang terselip di otot-otot. Itu tadi cangkul dan sabit sudah dibawa kakak-kakak laki-lakimu. Kang Yo, Kang So, dan Kang To sudah berangkat duluan.” Pagi-pagi Pak’e sudah memberikan instruksi. Tanpa basa-basi aku langsung bergegas menindak lanjuti perintah dari pimpinan tertinggi keluarga kami.
Pak’e adalah lelaki tiga zaman. Jaman Belanda yang sulit, jaman Jepang yang kejam dan jaman kemerdekaan yang masih butuh banyak perjuangan. Beliau adalah pejuang tak dikenal yang sempat ditahan Belanda di Penjara benteng Ambarawa karena memukul utusan Belanda hingga pingsan. Pada saat jaman Jepang, sebelum terlibat aksi Pertempuran Lima Hari di Semarang, Bung Tomo, begitu Pak’e biasa dipanggil oleh sesama pejuang, juga sempat ditahan beberapa waktu di Tangsi Jepang yang ada di daerah Kabluk, Semarang Timur. Masalahnya sederhana, salah strategi mengungkapkan teriakan kemerdekaan. Dikira yang dihadapan adalah kaum pribumi ternyata di belakangnya bersembunyi tentara Jepang. Padahal dengan pedang keramatnya beliau beberapa hari sebelumnya sempat membobol beberapa gerbong ransum beras Jepang di stasiun Poncol masingmasing dengan sekali tebas. Tebasan pedang sakti dengan pengerahan ilmu kanuragan itu sangat membantu rakyat jelata yang menderita kelaparan.
Setelah kampung pertamanya di Tambak Dalem dan toko kainnya di daerah Bon Knap di Jalan Mataram Semarang dibakar Jepang, beliau lebih memilih menetap di Widuri. Bertani dan memulai kehidupan baru. Di situlah kami sembilan bersaudara dilahirkan. Dua orang kakak tertua kami tidak sempat mengenyam kehidupan lebih lama karena sakit yang saat itu sulit ditemukan obatnya. Seandainya mereka berdua masih hidup tentu keluarga kami sangat ramai. Kami semestinya memiliki 11 orang anggota keluarga.
“Mikuwati dan Nyukupi, kalian gendong biji jagung dan biji kacang lanjar yang ada di dunak itu. Juga kendi dan godogan ketela pohon yang ada di atas gledeg di samoingmeja pawon,” Pak’e melanjutkan instruksinya kepada kedua orang kakak wanitaku.
“Sarapannya dihabiskan dulu,” sambungnya karena melihat mereka berdua ternyata masih asik menikmati sega kering yang dibeli dari warung Yi Muri. Warung satu-satunya di ujung kampung itu sangat terkenal dengan menu sega kering yang lezatnya melegenda seantero Widuri.
“Nggih Pak,” jawab keduanya hampir bersamaan. Kedua kakaku ini memiliki nama yang tak ada duanya. Unik seperti namaku dan nama adikku. Pak’e memang ezpert kalau soal memberi nama penuh makna. Beliau selalu nenjalani laku tirakat saat kami masih di dalam kandungan. Beliau juga konon menciptakan nama dwngan filosofi yang mendalam.
“Ayo, ndang rekat. Selak ditunggu Pakmu,” kata Mak’e menyemangati Yu Mi dan Yu Pi sambil nderesi daun pisang klutuk yang dipanen kemarin sore. Hujan deras semalaman menyebabkan daun daun lebar itu kuyup karena diletakkan di emper omah pawon. Daun harus ditata berdiri sebelum dideresi. Hari ini make prei berjualan hasil bumi karena turut membantu semua anggota keluarga yang sedang bersiap menanam palawija di tegalan depan rumah yang luas.
“Ganjarono, ndak usah bawa apa-apa ya Nang. Kamu kan masih kecil. Kamu boleh di rumah saja sama Mak’e atau ikut menangkap belalang,” kata Pak’e lagi pada adikku mengatur tugas kami satu persatu.
“Nanti kalau ada burung jalak berjalan-jalan didekatmu ditangkap aja ya. Burungnya masih kecil. Belum keluar giginya,” kata Pak’e sambil tersenyum.
Adikku mengangguk angguk senang. Ia bersemangat sekali. “Atu elu Kang Apu ae. Atu dicekelte anuk jalak yoh?” serunya sambil melonjak-lonjak kegirangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih dia bilang seperti ini, “Aku ikut Kang Mampu saja. Nanti ditangkapkan burung jalak ya. ” Ganjar bicaranya masih cedal. Usianya lima tahun, tiga tahun di bawahku. Ia belum sekolah.
“Hahahaha… Iyo Njar, ngko golek manuk dan belalang yang banyak ya, ” jawabku menghiburnya dan seisi keluarga tertawa geli. Suara tawa kami tertimpa kerasnya suara mainan otok-otok yang dimainkan maju mundur oleh Ganjar. Mainan dari bambu yang ditempeli kertas minyak warna warni dan bersuara nyaring itu dibelikan Mak’e pada saat lagan melek pasiang tetangga yang akan punya gawe. Orang paling kaya itu nanggap wayang dan tledek dua hari dua malam di kampung Widuri Selatan
Ganjar tidak tahu bahwa sebenarnya ia di-prank oleh Pak’e. Sewaktu masih seusianya aku juga pernah mendapatkan ucapan seperti itu. Dengan bersemangat aku segera mengejar burung jalak hitam yang banyak berkeliaran di halaman rumah. Tetapi ternyata tidak pernah berhasil. Aku pikir karena burung jalak itu belum keluar giginya maka mudah ditangkap. Ternyata burung jalak yang masih muda ataupun sudah tua memang tidak pernah keluar giginya. Dan burung jalak yang berani berjalan-jalan di tanah berdekat-dekat dengan manusia itu bukan burung anakan lagi. Burung itu sudah dewasa dan pandai terbang.
Kami membawa beberapa peralatan seperti ceblok, sabit, cangkul, dan bakul tempat benih. Ceblok adalah alat utama kami. Batang kayu dengan diameter kira-kira 5 cm dan panjang sekitar 1,5 meter itu diberi nama sesuai fungsinya. Ujung bagian bawahnya lancip dsedangkan bagian atasnya tumpul. Fungsi ceblok adalah untuk membuka tanah dengan cara nyeblok atau menancapkanya. Hasil tangcapan dengan kedalaman sekitar 3 sampai 5 cm tersebut kemudian diisi dengan butir-butir jagung.
Tanah yang lembab pada malam hari akan segera menumbuhkan biji-biji jagung yang kami tanam. Dalam waktu tiga setengah bulan berikutnya jagung-jagung itu sudah besar dan siap dipanen. Sebagian disimpan di atas para-para sebagai bibit untuk ditanam pada mangsa labuh tahun depan. Sebagian lagi dikonsumsi dan dijual ke pasar.
Di mangsa labuh tentu yang tumbuh tidak hanya jagung. Tuhan menciptakan berbagai macam vegetasi yang juga tumbuh subur tanpa perlu ditanam. Rumput-rumput liar yang selama musim kering seperti sudah punah, dengan datangnya mangsa labuh, semuanya menghijau kembali. Ada rumput teki, alang-alang, lamuran, daun apa-apa, lingi, glagah, tomplek, tembelekan, patik emas, krokot, ciplukan, dan lain-lain. Semua bangkit bersama, menghias tanah pusaka sehingga pemandangan yang ijo royo-royo tersebar dimana-mana.
Menjadi suburnya tanah menyebabkan suburnya tanaman. Suburnya tanaman juga menjadi sebab perkembang biakan berbagai macam binatang yang dipiara oleh alam. Dari binatang kecil dengan kaki banyak sampai binatang besar berkaki dua dan empat semuanya bergembira menyambut datangnya masa kesuburan. Binatang-binatang herbivora yang mengandalkan tumbuhan sebagai makanannya dengan sendirinya akan berkembang biak dengan cepat ketika persediaan makanan berlimpah ruah.
Berlimpahnya jumlah tanaman menyebabkan berlimpahnya jumlah binatang herbivora. Berlimpahnya jumlah binatang pemakan tumbuhan ini juga menyebabkan berlimpahnya jumlah binatang karnivora atau pemakan daging. Tumbuhan dan binatang-binatang itu saling berhubungan sebagai rantai makanan yang tidak terputus. Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa mengaturnya sedemikian rupa sehingga keseimbangan alam di bumi terjaga.
Keberlimpahan itu ditandai dengan berbagai fenomena alam. Semua seolah berpesta menyambut munculnya kembali berbagai sumber penghidupan yang melimpah ruah. Bunyi musang yang kasmaran, blacan yang menjerit bersenda gurau, garangan yang berkejaran, biawak yang saling buru, burung bubut dan srigunting yang berebut mangsa, atau belalang ecek-ecek yang menjerit-jerit tidak pandang siang ataupun malam hari. Semuanya menandai kebahagiaan akan kembali tumbuh suburnya alam. Pendeknya, semua binatang liar, dari yang melata, melompat, maupun terbang di angkasa semuanya mengalami kesuburan di saat bahan makanan mereka tersedia berlimpah di alam. Tak terkecuali serangga-serangga kecil yang hidup di alam bebas, seperti jangkrik misalnya.
Bagiku dan teman-teman sekampung, mangsa labuh merupakan musim menanam jagung sekaligus juga berarti musim jangkrik. Jangkrik-jangkrik itu membuat lubang di sekitar tanaman jagung yang baru tumbuh. Binatang mengerik itu biasanya memanfaatkan gundukan tanah bekas cangkulan yang runtuh oleh air hujan untuk lubang hunian. Tanah cangkulan itu memiliki banyak celah di dalamnya tetapi dari luar terlihat tertutup rapat. Yang terlihat hanya lubang kecil dengan diameter kurang lebih 2 centi yang menjadi jalan keluar masuk penghuninya.
Musim jangkrik selalu mendatangkan keasyikan tersendiri. Banyak pengalaman dari yang paling lucu sampai menakutkan yang kami alami ketika berhubungan dengan jangkrik. Kami mencari jangkrik tidak hanya siang hari. Bahkan di malam hari ketika jangkrik-jangkrik itu sedang bersuara kami akan mendatanginya dengan obor menyala untuk mengetahui lubangnya, lalu menangkapnya.
Jangkrik banyak sekali macamnya. Yang paling penting, harus dibedakan antara jangkrik jantan dan betina. Jangkrik jantan ditandai dengan sayap punggung yang berlekuk-lekuk, keras, dan sedikit menggembung. Sedangkan jangkrik betina sayap punggungnya rata, tetapi pada bagian belakang tubuhnya ada alat yang bentuknya seperti jarum. Panjangnya hampir 3/4 panjang tubuhnya. Secara keseluruhan penampilan jangkrik jantan lebih indah daripada yang betina. Jangkrik jantan juga bisa membunyikan sayapnya sedangkan jangkrik betina tidak.
Jenis-jenis jangkrik juga diberi nama yang berbeda-beda. Nama-nama jangkrik sudah dari sananya begitu. Aku menduga sebagian nama itu dimiripkan dengan ciri khasnya, misalnya warna, bentuk tubuh, atau bunyinya. Contohnya jangkrik kaji. Warna kepalanya merah menyala, berhias sedikit warna kuning agak putih terang seperti peci haji. Jangkrik jekethet itu bunyinya memang mirip kata “jeketit… jeketit”. Jangkrik ngerik atau aduan juga karena bunyi khas “krik..krik…” dan sifatnya yang mudah diadu. Lalu jangkrik gangsir bunyinya seperti “siiir… siirr” dan seterusnya.
Beberapa jangkrik yang sering aku temui memiliki nama yang berbeda-beda. Yang pertama ada jangkrik kaji yang kepalanya persis kepala luwing atau kaki seribu. Ukuran terbesar jangkrik ini bisa mencapai panjang tubuh 3,5 cm. Setahuku semua orang jijik dengan jangkrik jenis ini. Akibatnya jika kebetulan ada yang sedang mencari jangkrik dan menyasar bertemu jenis jangkrik ini biasanya sumpah serapah yang keluar dari bibir si pencari jangkrik. Mereka menuduh jangkrik kaji iti penipu, karena suaranya sangat mirip jangkrik aduan tetapi setelah liangnya dibongkar yang keluar ternyata jangkrik yang penampilannya menjijikkan.
Ada juga jangkrik lupa. Jangkrik jenis ini biasanya tinggal di celah-celah papan rumah. Ukurannya kecil-kecil tetapi antenanya sangat panjang. Panjang tubuhnya hanya sekitar 1 cm. Bunyinya cukup nyaring, sangat mirip bunyi jangkrik aduan. Pencari jangkrik juga sering terkecoh oleh bunyi jangkrik ini. Hobinya makan sisa nasi atau sisa-sisa makanan lain yang ada di meja makan di rumahku. Jika sedang berbunyi di pojok-pojok rumah dan mengerik, aku kadang juga salah mengira bahwa jangkrik itu adalah jenis jangkrik aduan yang juga biasa dinikmati bunyinya.
Selain itu ada jangkrik jeliring yang hobinya terbang mengitari lampu-lampu penerang. Ukuran tubuh jangkrik jenis ini bisa mencapai 2,5 cm. Jangkrik ini sayap dalamnya lebih panjang dan lebar dari jenis lain. Suaranya cukup keras tetapi tidak terlalu diminati. Biasanya untuk pakan burung.
Ada juga jangkrik jekethet yang bentuk badannya lebih pendek tapi kekar. Panjang tubuhnya dari kepala hingga ekor hanya sekitar 1,5 cm. Ukuran kepalanya yang cukup besar sering menipu. Para pencari jangkrik saat melihatnya mengintip dari lubangnya akan mengira itu jenis jangkrik aduan. Sayap luarnya kokoh dan keras. Paha pada bagian kaki lompatnya besar dan kuat.
Ada lagi yang namanya jangkrik gangsir. Jangkrik ini hobinya tinggal di lapangan. Lubang huniannya ditandai dengan sejumlah material galian tanah yang mengelilinginya sehingga menjadi gundukan yang cukup tinggi. Ukurannya paling besar diantara jangkrik yang ada di daerahku. Penampilannya seperti jangkrik kaji, tetapi besar dan panjang tubuhnya bisa dua kali lipatnya. Panjang tubuhnya bisa sampai 5 atau 6 centi. Beberapa orang kampung sering menangkapnya dan menjadikannya sebagai lauk.
Di antara jangkrik-jangkrik yang hidup di kampung Widuri, yang paling dicari adalah jangkrik aduan atau jangkrik ngerik. Secara penampilan, jangkrik jenis ini memang paling keren. Ukuran tubuh yang paling besar bisa mencapai 3,5 senti. Bunyi jangkrik ini sangat keras, saking kerasnya bahkan bisa untuk mengusir tikus. Selain itu jangkrik ini mudah dijadikan aduan. Rahang depannya yang sangat lebar dan kuat menjadi senjata andalan ketika menghadapi lawan. Makanan utamanya adalah rumput krokot. Tetapi bayam dan singkong dia juga tidak menolak.
Jangkrik ini memang jenis pemarah, makanya dijadikan jangkrik aduan. Dikili-kili sedikit saja dia akan langsung menyerbu maju. Rahangnya yang kokoh dengan taring-taring yang tajam segera terbuka lebar. Mereka bertarung dengan saling adu ketajaman taring dan kekuatan rahang. Sayap kerasnya akan ikut terangkat dan menimbulkan bunyi “krik…krik..” Biasanya alat untuk mengkili mulut jangkrik ini adalah bunga rumput teki. Sekali bunga itu dipilin didepannya, serbuan demi serbuan terus dilakukan jangkrik aduan itu.
Berdasarkan warnanya jangkrik jenis ini diberi nama-nama yang berbeda. Ada jangkrik jerabang yang warnanya merah seperti api. Lalu jangkrik jeragem yang merupakan perpaduan antara merah dan hitam. Terakhir adalah jaliteng, yaitu jenis jangkrik ini yang warnanya hitam legam.
Jangkrik-jangkrik jantan jenis ini jika dikumpulkan akan saling berkelahi. Tidak pandang bulu, mereka dari warna yang mana saja jika berhadapan muka akan langsung beradu taring. Sepanjang ada lawan untuk bertarung mereka akan terus saling serangsampai salah satu kalah dan lari terbirit-birit.
Itulah mengapa, anak-anak di kampung Widuri jika musim jangkrik tiba suka berkumpul menghadapi ember bersama-sama. Mereka bersorak sorai mengadu jagoannya masing-masing. Jangkrik-jangkrik jantan itu juga memiliki karakter seperti manusia. Ada yang kecil tapi pemberani. Ada juga yang besar tetapi penakut. Biasanya yang pemberani akan bertarung mati-matian. Walaupun sudah terluka, jangkrik nekat itu akan maju terus.
Ada juga yang nyalinya sedang-sedang saja. Begitu bertarung dan merasakan sakitnya derita pertempuran, jangkrik-jangkrik itu memilih menyingkir. Namun, anak-anak yang mengadu mereka tidak kurang akal. Mereka segera mencari rambut panjang untuk menjantur jangkrik-jangkrik itu. Begitu tubuh jangkrik itu dibelit dengan rambut dan diputar-putar di udara, sayapnya segera berkembang. Sambil berputar di udara jangkrik-jangkrik itu seperti terbang.
Dibutuhkan waktu 1 sampai 2 menit untuk memutar mutar jangkrik itu di udara. Karena diputar-putar, jangkrik-jangkrik itu akan mabuk dan lupa diri. Dari semula mundur karena kalah bertarung, jangkrik-jangkrik itu menjadi lebih berani. Tanpa rasa takut, jangkrik-jangkrik itu terus maju merangsek lawannya setelah dijantur.
Malam itu aku sudah berjanji untuk bertemu dengan Nur Kaji dan adiknya Dikatul. Mereka itu kakak adik tetapi sangat akur. Usianya hampir sepantaran. Tapi terlihat sekali kakaknya kelebihan gizi sedangkan adiknya kekurangan gizi. Kakaknya longgor, adiknya kontet. Kami berencana menangkap jangkrik aduan.
Siangnya sepulang sekolah kami sudah mempersiapkan alat-alatnya. Kami membuat tiga buah oncor atau obor bambu dan beberapa _duduk_ atau linggis dari bahan kayu. Beberapa pelok atau biji mangga golek dan kopyor kering yang sudah dihilangkan bagian dalamnya juga kami siapkan.
Pada mangsa labuh, sekitar Oktober-November itu musim mangga biasanya sudah mulai berakhir. Biji buah mangga yang berserakan dan sudah mengering biasanya kami kumpulkan. Jika isi bagian dalamnya yang merupakan bakal tunas kami ambil yang tersisa adalah kulitnya yang liat. Dengan membuka celah diantara Tangkuban kulitnya kita bisa memasukkan seekor jangkrik tangkapan ke dalamnya. Sebuah karet gelang cukup untuk mengikat pelok itu agar tertutup dan jangkriknya tidak melarikan diri.
Pelok itu hanya tempat sementara sebelum jangkrik dipindahkan ke dalam kanji. Kanji adalah tempat jangkrik yang terbuat dari susunan bambu-bambu kecil yang dibuat petak-petak seperti kandang. Masing-masing petak disediakan untuk seekor jangkrik. Makanan yang berupa daun krokot atau singkong disediakan di dalam petak-petak itu. Petak-petak itu dibuat supaya jangkrik-jangkrik itu tidak saling bercampur dan bertarung.
Malam itu selepas mengaji kami sudah bertemu di jalan di depan rumahku. Di bawah pohon kelapa yang biasa digunakan untuk memberondong petasan pada saat lebaran itu kami berembug. Kami sepakat untuk mencari jangkrik aduan di ladang kampung sebelah. Oncor-oncor sudah kami hidupkan. Api dengan cahaya berwarna kekuning-kuningan meliuk-liuk ditiup angin malam. Sebagian cahayanya menerangi muka kami. Di Belakang kami muncul bayangan bayangan raksasa berwarna hitam.
“Ayo berangkat, ” ajak Nurkaji.
“Jadi kita mencari jangkrik di ladangnya Lik Sumiah?” tanyaku memastikan.
“Kita lihat saja nanti.” Jawab Nurkaji penuh teka-teki.
“Ladang Lik Sumiah biasanya ada yang menjaga. Kita harus memastikan semuanya aman,” kata Dikatul menimpali.
Aku paling tidak suka kalau sedang mencari jangkrik lalu ketahuan yang punya ladang. Mereka akan berteriak-teriak dan memburu kami sambil mengacung-acungkan sabit. Kami akan segera lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mungkin bagi mereka kami dikenal sebagai anak-anak nakal. Padahal kami adalah anak-anak baik yang sedang bertualang. Kami sudah berjanji supaya tidak menginjak-injak jagung yang sedang tumbuh pada saat mencari jangkrik. Jika ada tunas yang rusak, itu biasanya justru perbuatan jangkrik.
Kantong celana kolor Nurkaji tampak penuh. Selain pelok yang dikantongi, Nurkaji juga membawa beberapa gendul pring. Itu adalah tabung yang terbuat dari potongan bambu yang diberi tutup serabut kelapa. Dia memang paling ahli menangkap jangkrik. Kira-kira ada 10 tempat jangkrik yang terbuat dari tabung bambu itu dia bawa. Dia dibantu oleh Dikatul adiknya.
Kami segera berjalan beriringan melewati jalan kampung yang gelap gulita. Lampu-lampu gembreng dan petromaks yang dinyalakan di rumah-rumah cahayanya tidak sanggup mencapai jalanan yang kami lewati. Rumah Lik Siyah yang lokasinya di ujung kampung malah sudah gelap gulita. Mungkin penghuninya pergi ke kampung Kuwaron. Perempuan tua itu biasa menginap di rumah anaknya di Kuwaron. Kampung Kuwaron hanya berjarak dua kilometer dari Widuri, kampung kami.
Tidak sampai 20 menit kami berjalan, kami sudah hampir sampai di lokasi sasaran. Sebuah ladang luas terhampar di hadapan kami. Tunas-tunas jagung muda bayangannya tampak menari-nari terkena sorotan cahaya oncor kami. Kami berhenti sejenak untuk mengatur strategi.
“Di. Kamu coba lihat gubug di depan itu,” perintah Nurkaji. Pada jarak 20 meter memang ada gubuk yang dijadikan tempat istirahat penjaga ladang. Dikatul harus memastikan gubug itu tidak ada penghuninya.
Lik Sumiah terkenal galak, tetapi jangkrik yang ada di ladangnya terkenal garang-garang dan jago di tempat aduan. Kami berencana bukan hanya mencari jangkrik di ladang tetapi juga di pematang. Konon jangkrik yang bisa membuat lobang hunian di pematang adalah jangkrik yang tangguh. Pematang tanahnya lebih liat daripada ladang yang sudah dicangkul gembur. Jadi jangkrik yang bisa membuat lubang di situ dipastikan memiliki energi lebih.
Di gubug itu tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara radio transistor ataupun cahaya lampu teplok. Meski begitu yang diperintah tampak bergeming. Dikatul tampaknya takut kalau sampai ketahuan maksudnya. Jika sampai diinterogasi oleh Lik Sumiah dan dilaporkan kepada Ayahnya, bisa habis mereka.
“Ayo sana jalan. Kamu kami awasi dari sini,” kata Nurkaji memerintah. Dikatul mengendap endap memdekati gubug. Wajahnya celingukan kayak bandit mau menyatroni rumah seorang juragan. Kami geli sendiri mengawasinya dari jauh. Setelah dipastikan tidak ada satupun penjaga di gubug itu Dikatul segera berteriak tertahan,“Hoi. Aman!”
Kami segera bergerak maju memasuki “medan pertempuran”. Suasana sangat riuh di ladang yang sangat luas dan jauh dari mana-mana itu. Kami siap berpencar mencari sumber suara jangkrik yang paling dekat dengan kami. Suara jangkrik yang bersahut-sahutan banyak sekali cukup membingungkan juga.
Jujur, malam itu sebenarnya aku merasa sangat bimbang. Aku tahu mencari jangkrik di ladang Lik Sumiah yang baru ditanami jagung adalah sebuah pelanggaran. Namun, begitu banyak jangkrik yang melimpah di sana. Kami membutuhkan jangkrik itu. Kami tahu risiko yang akan dihadapi jika ketahuan, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk mencapai tujuan kami begitu besar.
Di sisi lain, kami juga tahu bahwa jika sampai menginjak-injak tanaman yang baru ditanam, itu adalah sebuah kesalahan besar. Kami tentu tidak ingin merusak tanaman yang telah dirawat dengan susah payah oleh pemilik ladang. Kami tahu mereka pasti akan marah jika tahu kami melakukan sesuatu yang merusak tanaman itu. Oleh karenanya kami tidak ingin menyebabkan kekecewaan pada mereka, tapi aku juga tidak bisa menahan hasrat kami untuk mencari jangkrik.
Mula mula aku merasa tertekan dengan dilema ini. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Aku merasa kesal dan frustasi dengan diriku sendiri. Aku merasa takut jika aku salah memilih, aku akan menyesalinya nanti.
Tapi aku tahu, kami harus menyelesaikan semuanya ini dengan bijak. Ambil ikannya, tapi jangan sampai membuat airnya keruh! Kami perlu berpikir secara matang dan mencari solusi terbaik. Kami tidak boleh mengecewakan orang tua kami , tapi aku juga harus bisa mencapai tujuan kami. Kami harus menemukan cara untuk memenuhi hasrat kami tanpa merusak tanaman yang baru ditanam itu.
Aku merasa terjebak beberapa waktu di dalam dilema itu. Tetapi aku tahu, aku harus mengambil keputusan secepatnya. Aku berhenti sejenak di pematang. Nurkaji dan Dikatul yang sudah melangkah masuk dan berdiri di tepian ladang ikut berhenti. Wajah mereka bertanya tanya di bawah cahaya oncor yang melenggak lenggok. Mereka tahu aku masih ragu-ragu.
“Kenapa Lik Mampu? Kok berhenti?” tanya mereka berdua sambil mendekatiku.
Aku diam saja. Aku berharap bisa menemukan jalan keluar dari konflik batin ini. Aku berharap bisa menemukan cara untuk memuaskan keinginan dan mencapai tujuanku tanpa merusak apapun di sekitar ku. Aku perlu mencari solusi terbaik, dan aku tidak akan berhenti mencari sampai menemukannya.
“Sik Di, Nur.” kataku sambil berpikir keras. “MIsalnya kita tidak usah masuk ke ladang bagaimana?” tanyaku pada mereka.
“Terus?” bersamaan mereka bertanya.
“Mosok sudah kepalang basah begini kita mau pulang?” protes Nurkaji.
“Iya. Tiwas kami membawa bawa oncor sama wadah jangkrik banyak banyak. Jebule Lik Mampu apuci wae,” kata Dikatul kecewa. “Bubar Pakde. Bubar!” katanya sambil balik kanan. Langkahnya akan diikuti Nurkaji yang lengannya segera aku pegang.
“Tunggu sebentar!” kataku.
“Tunggu apa lagi Lik. Yuh pulang saja,” Dikatul yang terlanjur kecewa berniat benar benar meninggalkan tempat. Aku segera melompat mencegahnya. Kuhadang jalannya dan ia kuberi isyarat untuk berembug dulu.
“KIta berembug dulu. Jangan nesu begitu,” kataku. “Begini loh. KIta tetap mencari jangkrik tapi yang kita cari adalah jangkrik yang hebat dan kuat,” kataku melanjutkan.
“Tenane Lik?” sambil bertanya Dikatul matanya berbinar binar.
“Dengerin dulu Di,” kata Nurkaji. Dikatul mengangguk angguk.
Akhirnya kami sepakat bahwa kami harus mencari jangkrik istimewa. Jangkrik yang suara kerikannya banding dan kalau di gelanggang aduan selalu menang. Jangkrik yang kami butuhkan adalah yang bertubuh kuat, berbadan besar dan atletis, sekaligus pemberani. Jangkrik-jangkrik itu biasanya membuat liang di pematang. Jadi kami memutuskan untuk cukup bergerak di pematang saja dan tidak masuk ke ladang Lik Sumiah. Jangkrik yang hebat kami akan dapatkan, tetapi kami juga tidak akan membuat kesalahan dengan menyebabkan kerusakan tanaman jagung di ladang. Kami bertiga setuju.
Misi segara dijalankan. Kami kembali menyebar. Mencari sumber suara jangkrik yang bertebaran di pematang. Kami tidak lagi menghiraukan suara jangkrik yang ada di tengah ladang. Dua orang temanku itu lebih suka memilih jangkrik jerabang dan jaliteng. Sedangkan aku lebih suka jragem. Namun tentu saja kami tidak bisa memilih pada saat menangkap jangkrik. Masing-masing tergantung rezekinya. Rezeki jangkrik adalah ditangkap oleh siapa. Rezeki kami adalah menangkap jangkrik yang mana.
Malam semakin larut. Aku sudah mendapatkan beberapa ekor jangkrik. Tetapi ukurannya belum memuaskanku. Ada seekor jangkrik dengan suara keras dan ukuran tubuhnya besar. Pada saat liangnya aku bongkar di dalamnya banyak jangkrik betinanya. Rupanya itu adalah jangkrik jerabang jenis Don Juan. Sayangnya jangkrik itu sudah tua. Hal itu bisa dilihat dari tumbuhnya rambut di bagian belakang tubuhnya yang banyak sekali. Selain itu, si tua yang playboy ternyata hanya punya satu kaki. Bagi kami, jangkrik cacat, walau sekeren apapun, tidak akan pernah menarik hati kami. Sebesar apapun ukurannya dalam pertarungan hampir pasti tidak akan pernah menang.
Aku bergerak lagi, kutinggalkan Don Juan tua itu. Mengendap-endap menuju suara jangkrik di tengah tegalan yang bunyinya paling nyaring. Dua temanku aku beri isyarat supaya menyingkir karena aku yang mendeteksi bunyi jangkrik itu lebih dahulu. Keduanya menyingkir meski sambil menggerutu.
Langkahku kuatur sehati-hati mungkin, sebab suara berisik sedikit saja bisa mengagetkan jangkrik itu. Jika sampai bunyi kerikannya lenyap, alamat gagal total dan sia-sia sudah usaha pencarianku. Satu-satunya navigator dimana kakiku melangkah menuju lubang persembunyian jeragem yang aku harapkan itu adalah suara kerikannya yang “banding” itu.
Sebuah gundukan yang bersebelahan dengan tunas tanaman tomplek yang mulai menghijau menjadi fokus perhatianku. Suara kerikan itu terdengar keras sekali dari baliknya. Rupanya itu bukan gundukan hasil cangkulan. Gundukan itu muncul alami karena sebelumnya tempat itu merupakan tempat tumbuh pohon jati yang sudah mati.
Itu artinya jangkrik yang membuat lubang di dalamnya kekuatannya lebih besar dari sekedar jangkrik yang membuat lubang di pematang. Jangkrik itu bekerja dua kali lebih keras pastinya. Melobangi tanah pematang yang keras sekaligus menundukkan liatnya tanah yang bercampur batu di sekitar tunggakan pohon jati.
Aku melangkah sedikit memutar untuk memastikan lubang hunian di mana si jangkrik sedang pamer suara kerikannya. Sebuah lobang yang cukup besar nampak menganga di sisi gundukan. Begitu sinar obor mengenai lubang selebar lima sentimeter itu, suara kerikan yang keras itu seketika berhenti.
“Jeragem!” sorakku di dalam hati. Sepintas lalu tampak kepala jangkrik yang besar dengan punggung yang kokoh menyelinap ke dalam lubang. Rupanya menyadari adanya bahaya mengintai, jangkrik itu segera diam dan beranjak ke celah yang lebih dalam.
“Aha…mau kemana kamu nak…?!” bisikku sambil menyiapkan kayu penggali. Oncor segera aku tancapkan di sebelah gundukan dan aku mulai menggali. Perlahan namun pasti aku tusukkan ujung kayu penggali itu ke sisi kanan lubang. Dengan sekali ungkit terbukalah bagian dalam rumah sang jeragem.
“Ssshhhhh….!!” berbarengan dengan terbukanya tanah itu tiba-tiba terdengar bunyi mendesis. Tempat di hadapanku tanpa seekor ular dumung irus besar berwarna hitam. Ular jenis kobra itu menegakkan lehernya yang bergambar pola seperti tato berwarna merah kecoklatan.. Jeragem yang aku cari itu sudah tidak ada lagi, sebagai gantinya seekor cobra siap mengejar dan menyerangku.
“JANGKRIK TUNGGOOOON…!!!” Tanpa pikir panjang aku berlari sambil berteriak ketakutan. Aku tidak peduli dengan tempat jangkrik tangkapanku, oncor dan duduk yang aku pegang. Semuanya kutinggalkan. Melihat aku berlari ketakutan, dua temanku tanpa pikir panjang terbirit-birit mengikuti aku yang mengambil langkah seribu.
Kata tunggon adalah kata yang menyeramkan bagi kami. Maka kata itulah yang aku teriakkan setelah melihat jangkrik berubah menjadi ular kobra. Setelah merasa aman aku berhenti. Aku masih tersengal-sengal ketika semerbak bau pesing menyeruak. Rupanya ketakutan Dikatul lebih hebat dari ketakutanku. Karena saking takutnya tidak terasa celana pendek Dikatul basah. Dia terkencing-kencing di celana saat berlari sebelumnya. Kami pulang ke rumah masih dalam kondisi ketakutan dan ngeri dengan pengalaman malam itu. Kesialan kami tidak hanya berhenti sampai di situ. Kami harus merelakan kehilangan tempat jangkrik tangkapan beserta isinya, oncor, dan sandal japit kami.
Sejak saat itu kami memilih mencari jangkrik di siang hari saja. Kami mencarinya juga berkelompok saling berdekatan. Kami kapok jika sampai bertemu dengan jangkrik yang bisa berubah menjadi ular kobra lagi.
__________________________________
Draf Ditulis di Sampangan dengan metode Menemu Baling, menulis dengan mulut dan membaca dengan telinga, menggunakan aplikasi Batu Asimtut (Baca Tulis Aslinya Simak Tutur).
Belalang ecek-ecek = sejenis belalang dengan suara berisisk yang keras sekali Boding = sejenis golok Ceblok = kayu unyuk menancap deleg, gambas, waluh, bistru = namanama berbagai jenis labu Dicebloki bonggol = di tanami ketela pohon, dideresi = dipisahkan lembar daun dari tangkainya Dikoak = di buat cekungan, Dunak = wadah terbuat dari anyaman bambu Gledeg = semacam almari kabinet kayu Jeliring, jekethet, gangsir, lupa, kaji, ngerik = jenis jangkrik Kacang lanjar = kacang panjang Kang = panggilan untuk kakak lakilaki Kendi = tempat air minum dari tanah liat Lagan = bergotong royong di tempat yang punya gawe Mak’e = panggilan ibu Mangsa labuh = permulaan musim penghujan Melek pasiang = satu malam sebelum hari H punya gawe Otok-otok = mainan dari bambu yang menghasilkan suara toktok keras sekali Otot-otot = kayu penghubung antar tiang untuk menempelkan dinding papan. Pak’e = panggilan bapak Pawon = dapur Rekat = bersegera Sega kering = Nasi oseng tempe Selak = segera, semende = bersandar Tledek = tayub Yu = panggilan kakak perempuan
UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK PADA CERPEN
Unsur intrinsik cerpen penting untuk membangunnya kisah karena asalnya dari dalam cerita itu sendiri. Ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Akan tetapi, sebuah cerpen juga memerlukan unsur ekstrinsik sebagai pelengkapnya.
Dengan kata lain, cerpen adalah sebuah karya sastra yang relatif singkat atau dapat habis dibaca dalam sekali duduk. Di dalamnya menggunakan alur tunggal dan hanya berfokus pada satu tokoh atau peristiwa puncak.
Lantas, apa sebenarnya unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen hingga komponen yang menjadi perbedaan mendasar dari keduanya tersebut? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.
UNSUR INTRINSIK Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasan Komponen-komponen unsur intrinsik:
1. Tema Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik cerpen tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Biasanya, tema dari unsur intrinsik cerpen ini kelihatan jelas dalam cerita, tetapi bukan lewat ungkapan langsung. Untuk menentukan tema dari sebuah cerpen, kamu perlu membaca dari awal sampai akhir dulu.
2. Tokoh atau Penokohan Dalam cerpen tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik.Proses dalam menciptakan karakter atau citra sebuah tokoh dalam cerpen disebut penokohan, yang biasa dikenal sebagai tokoh yang antagonis, protagonis, tritagonis, dan tokoh figuran.Melalui penggambaran dan perilaku tokoh tersebut, maka cerita dapat menjadi lebih dramatis dan menarik untuk dibaca.
3.Alur Cerita Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab, sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, mundur, dan campuran.
4.Latar Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar atau yang biasa disebut dengan setting. Latar tersebut terbagi menjadi tiga yakni waktu, tempat, dan suasana.
5. Sudut pandang Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri tiga, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Paling sering, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tau segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita.
6. Gaya Bahasa Dialog, naskah atau percakapan dalam cerita memiliki style atau gaya bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari tema atau kategori cerpen yang ditulis.Gaya bahasa memiliki beberapa jenis, antara lain: Personifikasi = Pengumpamaan benda mati sebagai manusia (Wajahmu bersinar bagai rembulan). Metafora = Perbandingan kata yang bukan sebagai arti sebenarnya (Tulang punggung, murah tangan, murah senyum, dll). Hiperbola = Suatu ucapan atau gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi (Gedung pencakar langit, menangis darah, dll). Litotes = Gaya bahasa yang bertujuan untuk merendah (“Maaf hidangannya hanya segini, silakan dinikmati ala kadarnya”, “Bantuan ini tidak seberapa, tolong diterima”, dsb). Simile = Menggambarkan suatu kondisi dengan membandingkan satu hal dengan hal lainnya dalam satu kalimat (Kasih sayang ibu ibarat sedalam lautan, Wajahnya merona layaknya bunga mawar yang elok, dsb). Fungsi dari gaya bahasa sendiri yaitu untuk membuatnya cerita dalam cerpen terasa lebih nyata (real) dan menarik pembaca, serta mempertegas gagasan dalam cerita pendek.Gaya bahasa juga kadang dikenal dengan sebutan majas atau kiasan.
7. Amanat Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya,tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah, dan semangat mempertahankan kemerdekaan.
UNSUR EKSTRINSIK CERPEN Setelah membahas mengenai Unsur Intrinsik, kini mari kita bahas mengenai Unsur Ekstrinsik yang terdapat dalam cerita pendek.Jika unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dan mampu membangun cerita dari dalam, maka unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang juga mampu mendukung dan mempengaruhi sebuah cerita pendek, melalui nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis.
Banyak sekali hal-hal dari luar yang mampu menjadi unsur ekstrinsik dalam cerpen, seperti berikut ini:
1. Latar Belakang Masyarakat Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentunya nilai ekstrinsiknya. Ada pun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain: Ideologi negara Kondisi politik Kondisi sosial Kondisi ekonomi
2. Latar belakang pengarang Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen.Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya.
3. Nilai-nilai Nilai adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya.
Jurnal Sasindo UNPAMProgram Studi Sastra IndonesiaUniversitas PamulangJalan Surya Kencana 1, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417
Email : [email protected]
Suka baca cerpen? Yuk, lihat beberapa contoh cerpen singkat dan menarik, beserta pengertian dan strukturnya di artikel Bahasa Indonesia kelas 9 berikut ini!
Sejak kecil, kamu pernah membaca cerita-cerita pendek mengenai putri dan pangeran, nggak? Semua cerita itu sangat seru dan membekas di ingatan sebagian besar orang hingga sekarang. Yap, cerita pendek atau cerpen memang seperti memiliki kekuatan sihir yang membuat kita sulit lupa.
Tapi, tahukah kamu apa itu cerpen? Lalu, cerita seperti apa yang dapat kita katakan sebagai cerpen? Nah, supaya nggak bingung, simak pengertian, struktur, beserta contoh cerpen singkat dan menarik berikut ini!
Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Selain itu, cerpen juga hanya memuat satu alur cerita. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 hingga 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500–10.000 kata. Maka dari itu, cerpen sering juga disebut sebagai “cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk”.
Biasanya, cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga ke renungan yang dipotret dari kehidupan nyata. Namun, tokoh dan latar bisa direkayasa demi kepentingan keindahan cerita sekaligus membedakannya dari teks pengalaman nyata.
Ciri cerpen juga ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil. Nah, unsur yang ada pada cerpen adalah tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan plot, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Cerpen juga memiliki memiliki struktur dalam penulisannya.
Baca Juga: Mengupas Cerpen: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Struktur, dan Analisisnya
Dalam artikel ini, kita akan fokus membahas tentang struktur yang dimiliki oleh cerpen. Apa aja sih struktur cerpen? Perhatikan di bawah ini ya.
Sudah tahu belum, di Aplikasi belajar Ruangguru, ada fitur Drill Soal yang berisi kumpulan contoh soal latihan beserta pembahasannya, loh. Pas banget kan buat mempersiapkan diri kamu dalam menghadapi ujian nanti. Yuk, klik banner di bawah ini untuk coba fitur Drill Soal!
Struktur cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, ada di bawah ini!
Di bagian ini, kamu akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antartokoh.
2. Rangkaian Peristiwa
Kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga.
Kemudian, cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter
Bagian ini akan menceritakan solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai telah berhasil. Pada bagian ini, kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita.
Oke, setelah kita mengulas kembali mengenai pengertian dan struktur cerpen, berikut ini ada beberapa contoh cerpen singkat. Kita baca sama-sama, yuk!
Cerpen berjudul Macan
Oleh: Seno Gumira Ajidarma
Malam berhujan di hutan baik untuknya. Ini membuat manusia kurang waspada karena titik-titik hujan pada setiap daun menimbulkan suara di mana-mana di dalam hutan sehingga pendengaran mereka teralihkan. Apalagi jika manusia ini alih-alih memburu dirinya, malah bercakap-cakap sendiri, mungkin untuk menghilangkan ketakutan dalam kegelapan tanpa rembulan.
Ia merunduk di balik semak, antara bersembunyi tetapi juga siap menerkam. Iring- iringan manusia berjalan berurutan di jalan setapak di bawahnya. Di sisi lain jalan terdapatlah jurang berdinding curam yang menggemakan arus sungai di dasarnya. Suara arus tentu lebih mengalihkan perhatian. Gemanya bahkan membuat mereka harus berbicara cukup keras.
”Hujan begini Simbah tidak ke mana-mana kan?”
”Oooh kurasa hujan seperti ini tidak banyak artinya untuk Simbah, justru ini saatnya keluar untuk mencari mangsa yang menggigil kedinginan.”
”Berarti mangsanya itu kamu!”
Baginya ini hanya suara-suara karena ia memang tidak mengerti bahasa manusia. Namun, ia memang bisa memangsa salah seorang di antaranya. Ada sebuah celah di antara dua pohon besar di ujung jalan setapak ini, yang membuat mereka harus berhenti sejenak ketika satu per satu melewatinya. Setelah melangkahi akar-akar yang besar, setiap orang akan menghilang di baliknya. Akar- akar pohon sebesar itu memang tidak bisa dilangkahi, akar-akar itu harus dipanjati, seperti memanjat pagar tinggi lantas menghilang di baliknya dan tidak terlalu mudah untuk segera kembali lagi.
Itulah saat terbaik untuk menerkam manusia yang paling belakang. Membuatnya terjatuh dan menggigit lehernya sampai lemas dan mati. Itu tidak dilakukannya. Untuk sekadar membunuh ia cukup muncul dan menggeram. Melihatnya menyeringai, manusia yang terkejut dan melangkah mundur akan terperosok dan melayang jatuh ke dasar jurang tanpa jeritan.
Ini juga tidak dilakukannya. Ia hanya merunduk dan mengintai. Ia tidak berminat membunuh manusia, bahkan tidak satu makhluk pun, selain yang dibutuhkannya untuk menyambung kehidupan—dan saat ini ia tidak kelaparan karena sudah memangsa seekor kancil tadi siang. Kancil bodoh itu seperti lupa bau kencing pasangannya, bapak anaknya, yang pada setiap sudut menandai wilayah mereka. Adalah wajar bagi mereka untuk memangsa makhluk apa pun yang memasuki wilayahnya. Dengan hukum itulah, nasib sang kancil sudah ditentukan.
Sebetulnya sudah lama bagaikan tiada makhluk apa pun akan memasuki wilayah mereka itu. Tidak babi rusa, tidak kijang, tidak pula burung-burung dan serangga. Pasangannya mesti mencari mangsa ke luar wilayah, begitu jauhnya sampai keluar dari hutan.
”Kambing kita lama-lama bisa habis dimakan Simbah,” kata salah seorang.
Namun bukanlah ketakutan atas habisnya kambing, yang membuat orang-orang kampung masuk hutan mencarinya.
Pada suatu hari pasangannya muncul dari dalam hutan di tepi ladang. Langsung didekatinya sesuatu di atas tikar, sesuatu di balik kain yang bergerak-gerak. Bagi makhluk besar yang lapar, makhluk kecil bisa terlihat sebagai santapan.
Lantas terlihat olehnya bayi manusia itu. Menatapnya sambil tertawa-tawa. Hanya makhluk manusia yang bisa tertawa di dunia ini, dan itu membuatnya tertegun.
Saat itulah dari tengah ladang mendadak terdengar suara bernada tinggi yang disebut manusia sebagai jeritan.
Malam tanpa rembulan semakin kelam. Hujan tidak menderas tetapi tidak juga mereda. Ia memperhatikan orang-orang itu menjauh. Mereka semua, dua belas orang bercaping maupun berpayung daun pisang membawa tombak dan parang serba tajam. Keriuhan mereka tidak akan menghasilkan tangkapan apa pun karena tiada seorang jua dari mereka adalah pemburu.
Ia tahu bukan orang-orang itu yang menjadi penyebab kematian pasangannya, melainkan pemburu yang masuk sendirian ke dalam hutan tanpa suara meski tubuhnya penuh senjata. Tombak di tangan, parang dalam sarung di punggung, pisau belati di pinggang kanan, dan umban di pinggang kiri.
Pemburu itu bahkan tidak bergumam. Membaca jejak di tanah, berjalan melawan arah angin, makan seperlunya dan tidak memasak di dalam hutan. Jika mulutnya bergerak- gerak barangkali mendesiskan rapalan.
Tentu pemburu itu telah melacak jejak semalaman ketika dengan tiada terduga, tetapi penuh rencana, muncul di depan gua batu tempat ia sedang menyusui anaknya. Ia segera menggeram dan berdiri melindungi anak jantannya. Pasangannya bahkan melompat dan menerjang ke arah pemburu itu, tetapi makhluk yang disebut manusia ternyata tidak hanya bisa tertawa, tetapi pandai memainkan tipu daya.
Sangatlah mudah bagi pasangannya untuk menyusul pemburu itu ke tepi hutan, menyeberangi ladang, dan siap menerkamnya di tengah lapangan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya selain menggeram-geram ketika ternyata muncul puluhan manusia mengepung sembari mengacung-acungkan tombak bambu ke arahnya. Pasangannya mencari celah, berputar-putar dalam kepungan yang semakin merapat, sampai hampir semua tombak itu menembus kulit lorengnya.
Orang-orang berteriak lega atas nama keselamatan anak manusia, kambing, sapi, ataupun kerbau mereka, meski dalam kenyataannya kambing, sapi, dan kerbau di kampung itu lebih sering diambil, dibantai, dan dikuliti di kandangnya sendiri oleh para bapa maling berkemahiran tinggi. Kawanan bapa maling datang lewat tengah malam mengendarai mobil boks. Dengan mantra dalam campuran bahasa asing dan bahasa daerah yang tidak pernah digunakan lagi, mereka menyirep seisi rumah yang di kampung itu jaraknya saling berjauhan. Pagi harinya hanya tinggal isi perut ternak berserakan dengan bau anyir darah di mana-mana.
Kambing yang diterkam penghuni rimba jumlahnya tidak seberapa dibanding pencurian ternak dengan mobil boks. Itu pun bisa terjadi karena kelalaian pemiliknya, jika tidak pintu kandang terbuka, sering diikat begitu saja di luar kandang, sehingga menjadi sasaran empuk makhluk pemangsa dari masa ke masa.
Bahwa bayi manusia seperti akan menjadi mangsa itulah yang mengubah segalanya.
”Akhirnya terbunuh Si Embah ini!”
Pemburu itu tidak berteriak, tetapi pengaruhnya lebih besar dari segala teriakan.
”Belum? Kita baru saja merajamnya begitu rupa sampai kulitnya tidak bisa kita jual.”
”Masih ada betinanya….”
”…dan masih ada anaknya.”
Saat pasangannya itu tewas oleh puluhan bambu tajam, ia yang ternyata mengikuti dari belakang dapat menyaksikan dari kejauhan. Saat itu tidak ada satu pun di antara para manusia melihat ke arahnya. Tanpa bisa memberi bantuan, ia hanya berjalan mondar- mandir dengan gelisah.
Ia masih berada di sana ketika menyaksikan betapa orang-orang kampung itu tetap menguliti pasangannya, dan membawanya pergi dengan mempertahankan agar kepalanya tetap tersambung pada kulit loreng tubuhnya. Katanya bisa menjadi hiasan dinding kantor kelurahan.
”Kita harus membunuh juga betinanya, ia pasti juga akan mencari mangsa di kampung kita!”
”Anaknya juga harus kita bunuh, kalau tidak tentu setelah dewasa membalas dendam!”
Ia memang tidak memahami bahasa manusia, baginya itu hanya berarti suara-suara, tetapi nalurinya dapat merasakan ancaman.
Kini dalam kelam berhujan, ia mengawasi orang-orang yang memburu dirinya itu dari suatu jarak tertentu. Ia telah memindahkan anaknya ke goa lain yang sama hangatnya pada malam hari, dan karena itu ia tidak perlu khawatir mereka akan menemukannya. Pemburu itu mungkin akan bisa, tetapi tidak malam ini, karena belum tahu bahwa goa yang ditemukannya sudah kosong.
”Betinanya baru saja beranak, dan anaknya masih terhuyung-huyung kalau berjalan….”
Pemburu itu memberi petunjuk ke mana orang-orang kampung bisa menyergap makhluk pemangsa yang terandaikan bisa membalas dendam.
”Anakku sakit panas,” katanya memberi alasan. Dalam hatinya ia sudah bosan bekerja tanpa bayaran.
Demikianlah rombongan orang-orang bertombak yang bercaping ataupun berpayung daun pisang muncul di ujung jalan setapak di tepi jurang ketika ia berada dalam perjalanan memburu pemburu.
Ia merunduk di balik semak, membiarkan mereka lewat, dan membuntutinya sejenak untuk memastikan arahnya. Ia tidak membunuh seorang pun.
Setibanya di kampung yang gelap dan sunyi di malam berhujan tanpa rembulan, sembari melangkah tanpa suara, terendus olehnya aroma pemburu yang tengik itu dibawa angin dari sebuah rumah terpencil. Sebuah rumah yang sengaja berjarak dan menjauhkan diri karena penghuninya yang selalu berikat kepala kusam merasa berbeda dari para petani bercaping.
”Orang-orang dungu,” pikirnya selalu.
Terdengar tangis bayi yang tak kunjung berhenti.
”Panasnya belum juga turun, coba ambilkan air yang lebih dingin dari sumur, handuk ini seperti baru tercelup air rebusan,” ujar perempuan yang sedang menjaram anaknya itu.
Kemudian pintu rumah kayu itu terbuka. Dari dalam membersit cahaya lentera. Seorang lelaki berikat kepala dengan bau tubuh yang tengik berlari kecil ke arah sumur sambil membawa baskom.
Hujan belum berhenti ketika ia meluncurkan ember pada tali timba ke bawah dan mengereknya kembali ke atas secepat-cepatnya.
Dalam kesibukan seperti itu pun, kepekaannya sebagai pemburu tidak pernah berkurang. Ia melepaskan tali timba dan membalikkan badan secepatnya.
Namun, kali ini sudah terlambat.***
Cerpen berjudul Sesaat Sebelum Berangkat
Sesaat Sebelum Berangkat
Aku menutup kembali pintu lemari pakaian. Isak tangis tertahan masih terdengar dari luar kamar. Tanganku meraih daun pintu, menutup pintu kamar yang terbuka sejengkal. Suara tangisan tinggal lamat-lamat.
Aku berjalan pelan menuju jendela, membukanya, lalu duduk di atas kursi. Pagi ini, langit berwarna kelabu. Sejujurnya, sempat melintas pertanyaan di kepalaku, kenapa aku tidak menangis? Kemudian pikiranku mengembara, menyusuri tiap jengkal peristiwa yang terjadi tiga pekan lalu.
”Kamu belum pernah punya anak. Menikah pun belum. Kalaupun toh punya anak, kamu tidak akan pernah punya pengalaman melahirkan. Kamu, laki-laki.”
Aku menatap wajah di depanku, wajah perempuan yang sangat kukenal.
”Aku, ibunya. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Kelak kalau kamu punya anak, kamu akan tahu bagaimana rasanya khawatir yang sesungguhnya.”
Pelayan datang. Ia meletakkan dua buah poci, menuangkan poci berisi kopi di gelasku, beralih kemudian menuangkan poci teh di gelas perempuan di depanku. Pelayan itu lalu pergi setelah mempersilakan kami menikmati hidangannya.
”Apa yang dia lakukan selama seminggu berada di tempatmu?”
”Kami banyak jalan-jalan berdua, menonton film, ke toko buku, ke pantai. Kebetulan aku sedang tidak sibuk. Aku pikir, ia sedang liburan sekolah.”
”Sekolah tidak sedang libur, dan ia tidak pamit kepadaku.”
”Dan kamu tidak memberitahuku.”
”Aku pikir ia pergi dengan seizinmu.”
”Kamu bohong. Kamu tahu kalau ia minggat dari rumah.”
Aku diam. Tidak mau memperpanjang urusan pada bagian ini. Aku datang tidak untuk berdebat. Tiga perempuan masuk ke ruangan ini. Bau harum menebar ke seluruh penjuru ruangan.
Perempuan di depanku mendesah. Tangannya meraih tas, mengeluarkan sebungkus rokok, menyulutnya.
”Ia boleh kacau, tetapi tidak boleh minggat. Ia masih duduk di bangku kelas satu SMA!”
Aku tertawa. ”Kamu tahu, aku minggat pertama kali dari rumah saat kelas satu SMP…”
”Itu kamu. Setiap keluarga punya tata tertib yang tidak boleh dilanggar.”
”Minggat itu memang melanggar tata tertib keluarga. Dan itu pasti ada maksudnya. Tapi aku tidak mau bertengkar. Aku datang jauh-jauh ke sini, hanya untuk mengatakan sesuatu yang kupikir penting menyangkut dia.”
”Jangan terlalu memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya.”
”Hey, kamu hanyalah pamannya. Aku, ibunya!”
”Aku tahu, dan aku tidak sedang ingin merebut apa pun darimu.”
”Tapi kamu seperti sedang menceramahiku tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik!”
Suaranya terdengar memekik. Orang-orang menoleh ke arah kami. Kami diam untuk beberapa saat. Sama-sama merasa kikuk menjadi perhatian beberapa orang.
”Jendra, anak yang manis. Tidak sepertimu…” desisnya kemudian.
Aku mulai merasa darahku naik.
”Ia penurut, dan tidak pernah menyusahkan orangtua. Tidak sepertimu.”
Darahku semakin terasa naik.
”Aku tahu persis karena aku ini ibunya, ibu kandungnya!”
Dengan suara menahan marah, aku bertanya, ”Lalu kenapa dia minggat dari rumah?”
Perempuan di depanku diam. Ia mematikan rokok di asbak dengan cara yang agak kasar. Aku gantian menyulut rokok.
”Risa, aku akan membuka sedikit rahasia yang kusimpan selama ini. Hanya sekali saja aku akan menceritakan ini untukmu… Aku selalu bermimpi buruk, sampai sekarang. Dan mimpi buruk yang paling sering kualami, aku tidak lulus sekolah. Kadang aku bermimpi tidak lulus SMP, SMA dan tidak lulus kuliah.”
Ia tertawa. ”Wajar kalau kamu mimpi seperti itu, kamu kan agak bodoh dalam hal sekolah…”
”Bukan itu poinnya!” suaraku, mungkin terdengar marah. Risa seketika menghentikan tawanya.
”Aku tidak suka sekolah, dan aku harus menjalani itu semua. Memakan hampir sebagian besar waktu yang kumiliki… Aku masih bisa merasakan sampai sekarang, gedung-gedung kaku itu, lonceng masuk, upacara bendera, tugas-tugas, seragam, suara tak tok tak tok sepatu para guru…”
”Kamu memintaku agar Jendra tidak sekolah?”
”Dengarkan dulu… Dan apa gunanya itu semua bagiku sekarang ini? Tidak ada. Ini kehidupan yang gila, aku tersiksa berbelas tahun melakoni sesuatu yang menyiksaku, yang kelak kemudian tidak berguna.”
”Bagimu. Bagiku, sekolahku berguna. Juga bagi Jendra.”
”Tapi kamu bukan aku.”
”Kamu juga bukan Jendra. Ingat itu!”
”Aku hanya sedang menceritakan diriku!”
”Kupikir kamu datang jauh-jauh untuk menceritakan soal Jendra yang minggat dari rumah dan tinggal di tempatmu! Bukan untuk menceritakan sesuatu tentang dirimu yang jelas aku tahu…”
”Itulah kesalahanmu sejak dulu, merasa tahu persoalan orang!” Aku menatap kakak perempuanku. Mungkin sudah ratusan kali, sejak aku kecil untuk menempeleng wajahnya. Tapi belum pernah kesampaian.
”Tahukah kamu, kalau sejak kecil kamu selalu menyusahkan orangtua kita?”
Aku menarik napas panjang. Aku memandang cangkir kopi di depanku, dan ingin sekali melemparkan benda itu di mulut pedasnya.
”Dan tahukah kamu kalau sifat itu bisa menular?”
Kali ini, kupikir Risa sudah keterlaluan. ”Kamu pikir aku menularkan sifat burukku kepada Jendra?”
”Aku tidak bilang seperti itu. Kamu yang mengatakannya sendiri. Yang aku tahu, semenjak ia minggat dan tinggal di tempatmu, ia semakin berani kepadaku, semakin sering bolos sekolah dan tidak mau lagi mengikuti berbagai kursus!”
”Jadi kamu menuduhku sebagai biangnya!”
Risa hanya mengangkat bahunya. Dan tersenyum sinis. Aku benar-benar nyaris kehilangan kontrol. Untuk meredakan semua yang kurasakan, aku menuang kopi, menyeruput, dan menyulut lagi sebatang rokok.
”Jadi menurutmu, kenapa dia bisa minggat?”
”Mungkin dia ada masalah… Itu biasa saja. Kesalahannya yang paling fatal adalah… Ia minggat ke tempatmu!”
Begitu mendengar kesimpulan itu, aku merasa bahwa pertemuan ini akan berakhir dengan buruk. Rasa marah sudah benar-benar menjalar di dadaku. Tetapi aku sadar, sebelum keadaan ini bertambah semakin buruk, aku ingin mengatakan sesuatu yang harus kukatakan berhubungan dengan Jendra kepada Risa.
”Rif, kamu menikah saja belum.”
”Ris, tidak ada hubungannya hal itu dengan obrolan kita hari ini!”
”Ada! Mengambil beban tanggung jawab yang sesederhana itu saja kamu tidak sanggup, dan kamu ingin menceramahiku soal bagaimana mendidik anak…”
”Aku datang hanya untuk menyampaikan apa yang dikeluhkan Jendra kepada orang yang merasa bisa mendidiknya!”
”Apa yang dia katakan?”
”Dia ingin pindah sekolah.”
”Itu sekolah paling favorit.”
”Favorit menurutmu, tetapi tidak menurutnya.”
”Dia masih anak-anak… Dia belum tahu apa pentingnya ilmu.”
”Dia butuh jaringan untuk masa depannya, dan itu ada di sekolahnya!”
”Ya jelas menurutku, karena aku lebih banyak makan asam garam hidup ini. Dan punya tugas untuk memastikan dan menjamin masa depannya!”
”Ia ingin kursus bahasa Perancis.”
”Boleh. Tetapi dia tidak boleh meninggalkan kursus bahasa Mandarin.”
”Dia ingin kursus main drum.”
”Boleh! Tapi dia tidak boleh meninggalkan kursus belajar piano.”
”Kenapa dia tidak boleh memilih?”
”Karena dia belum bisa memilih.”
”Dia terlalu capek dengan itu semua…”
”Dia harus belajar bekerja keras dari sejak kecil. Disiplin. Itu yang akan menyelamatkannya dari persaingan di masa depan.”
”Kenapa kamu menyuruhnya memutuskan pacarnya?”
”Dia masih kelas satu SMA!”
”Kamu dulu pacaran ketika masih kelas tiga SMP.”
”Itu aku, bukan dia! Jendra itu, makan saja kalau tidak disuruh, tidak makan!”
”Kamu merasa lebih baik dan lebih hebat dari Jendra, hah?”
”Aku, ibunya! Rif, sudahlah… Kalau kamu punya anak, kamu baru bisa merasakan apa arti anak bagi orangtua. Rif, aku hanya minta, kalau dia datang lagi ke tempatmu, segera hubungi aku!”
”Ris, aku bawakan hasil penelitian seorang psikolog tentang tingkat stres para pelajar di kota ini…”
”Aku tidak butuh informasi itu.”
Kali ini, darahku benar-benar mendidih.
”Aku khawatir kelak kamu akan menyesal…” ucapku dengan nada mengancam.
”Kamu urus saja kehidupanmu. Jendra adalah urusan keluargaku.”
Pembicaraan terkunci. Dadaku bergolak. Kemarahanku sudah sampai pada pangkal leher. Aku hanya menekan-nekan dahi dengan tanganku. Aku ingin mengatakan apa yang sempat dikatakan Jendra kepadaku. Tetapi jika mulutku terbuka, aku khawatir gelegak itu akan membeludak.
”Kamu langsung pulang atau menginap?”
”Aku masih ada urusan kantor.”
Aku memberi isyarat dengan kepalaku, ia boleh pergi.
Ia bangkit, lalu melangkah pergi.
Ia menoleh. ”Sudahlah, Rif. Aku bisa mengurusnya.”
Ia kembali berjalan menuju pintu.
Aku bisa saja mengejarnya, dan mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Tetapi aku sudah terlalu marah. Dan aku juga membayangkan apa yang akan dikatakan Risa begitu mendengar apa yang seharusnya kukatakan. Ia mungkin hanya akan tertawa. Ia mungkin hanya akan semakin membuatku marah.
Perasaanku kacau. Aku keluar, menyetop taksi, pergi menuju ke bandara.
Aku bangkit, berjalan, membuka pintu kamar. Kudapati, Mita masih menangis si atas sofa. Ia melihat ke arahku. Aku berjalan, lalu duduk di sampingnya.
”Kenapa belum bersiap?” dalam isak, Mita bertanya.
Aku hanya diam. Mita memegang tanganku.
”Kita bisa ketinggalan pesawat…”
Aku hanya bisa menarik-narik rambutku ke arah belakang. ”Kupikir kamu saja yang berangkat.”
”Kenapa bisa begitu?”
Aku menatap wajah pacarku. ”Aku tidak sanggup datang.”
”Kamu tidak boleh begitu. Apa yang harus kukatakan kepada keluargamu?”
”Mereka tahu sifatku, jadi tidak usah khawatir.”
Aku menganggukkan kepala.
Mita bangkit dari sofa, perlahan menuju kamarku, merapikan diri. Sesaat kemudian dia keluar, meraih tasnya.
”Rif… Kenapa Jendra bisa melakukan ini semua?”
Aku diam. Lalu menggelengkan kepalaku. ”Sudahlah, nanti kamu terlambat datang ke pemakamannya.”
Mita melangkah pergi keluar.
Beberapa saat kemudian, aku membuka laptop di atas meja. Membuka berkas foto yang tersimpan di sana. Melihat kembali gambar-gambar Jendra terakhir di pantai bersamaku, sebelum keesokan harinya ia pulang kembali ke rumah orangtuanya.
Di malam sebelum pergi, sepulang dari pantai, ia sempat mengatakan apa yang ingin dilakukannya. Omongan yang seharusnya kusampaikan kepada Risa. Tetapi aku terlalu marah, dan takut semakin marah membayangkan apa yang akan dikatakan Risa begitu mendengar omonganku.
Kini, aku tidak berani membayangkan bagaimana jika yang terjadi sebaliknya, begitu aku sampaikan apa yang sempat terlontar dari mulut Jendra kepadaku. Bagaimana jika kemudian Risa peduli pada omongan itu dan mengubah sikapnya kepada Jendra?
Kini, aku menangis keras-keras di dalam kamar. Sendirian.***
Cerpen berjudul Ziarah
Oleh: Dewi Kharisma Michellia
Begitu tertera pada dua kayu nisan yang tertancap di puncak bukit pagi itu. Dengan cuaca yang sama, dua puluh tahun lalu, aku ingat betul, aku hampir tak mengenali separuh orang yang berdiri mengelilingiku di bawah payung-payung gelap mereka.
Melintasi sepanjang jalan setapak kembali ke rumah, aku ingat bagaimana aku dibawa pergi oleh mobil-mobil panjang besar, oleh orang-orang yang belum genap sehari kukenal. Tengah malam di waktu sebelumnya, keluarga bibi yang tinggal di sebelah rumah—satu-satunya tetangga yang ketika itu dekat dengan keluargaku—mengantarkan mereka kepadaku. Masih separuh terjaga di sebelah peti mati kedua orang tuaku, aku mendengar percakapan mereka, namun tidak kuteruskan.
Mereka menghampiriku dan memperkenalkan diri sebagai kerabat dari pihak ayah, tempatku berlindung setelah segala prosesi pemakaman orangtuaku berakhir. Saat itu aku sungguh takut.
Masih kuingat betul apa yang menyebabkan kedua orangtuaku berpulang. Saat mendapat kabar, sepulang dari berburu kelinci bersama teman-teman sebaya, aku berlari menyusuri jalan setapak berkilo-kilometer jauhnya, hanya untuk memastikan aku masih bisa menyelamatkan kedua orangtuaku.
Saat aku datang, api telah melahap gudang tempat ayahku biasa bekerja. Aku berkeliling ke dalam rumah, mencari ibu. Kudapati, para tetanggaku berusaha memadamkan api dengan baskom-baskom kayu berisi air. Beberapa dari mereka bilang ibuku juga terperangkap di dalam rumah.
Segala upayaku untuk dapat mencapai gudang digagalkan. Mereka berbondong-bondong memelukku dan menghentikan niatku menerobos api. Mereka menghentikan segala teriakanku dan mendekapku seerat mungkin.
Api akhirnya padam berjam-jam kemudian, dan yang kudapati sesudahnya hanyalah tengkorak ayah dan ibuku dengan sedikit sisa daging dan kulit yang terbakar, mereka terikat saling memunggungi pada tiang besi yang sebelumnya tak pernah kulihat. Satu yang kutahu. Pastilah Tuhan tidak dengan sengaja meletakkan besi di sana dan memanggang kedua orang tuaku di gudang itu. Pasti ada orang lain yang melakukannya.
Kurasa pekerjaan ayahkulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Hingga kini, aku tak mengerti apa yang dilakukan ayah di ruang kerjanya, padahal dulu ibu pernah bilang suatu saat aku akan tahu.
Hari ini, memasuki ruang tengah, sepenjuru rumah kayu itu telah dipenuhi tumbuhan merambat. Padahal dulu di sana aku pernah duduk, menantang dengan dada membusung, berhadapan dengan orang-orang yang tak kukenali siapa.
“Kami akan mengajakmu kembali.” Masih kuingat seorang pria jangkung berkulit bersih dengan kacamata bergagang bulat duduk di tengah-tengah, berhadap-hadapan denganku. “Di sana kakek dan nenekmu menunggu. Keluarga besar akan menghidupimu.”
Aku tak pernah tahu kakek-nenekku masih hidup. Ayah dan ibu tidak pernah menceritakan apa pun tentang masa lalu mereka, selama belasan tahun di awal hidupku, aku menerima kenyataan itu begitu saja; seolah orangtuaku benar terlahir dari batu.
“Saya tidak percaya.”
“Kami tahu kamu perlu bukti. Ayahmu dan istrinya mengasingkan diri mereka kemari segera setelah ayahmu menamatkan kuliah di Belanda. Dalam dokumen ini kamu bisa menemukan segala hal tentangnya.”
Saat itu ia menjetikkan jari dan beberapa orang pesuruh masuk ke dalam ruangan dengan mengangkat peti-peti besi di pundak mereka. Semuanya kemudian diletakkan di hadapanku.
Pria itu sedikit memundurkan badannya dan membukakan gembok yang mengunci peti dengan kunci kecil dari dalam sakunya, menunjukkan semua dokumen tentang kehidupan ayahku.
Aku terkesima. Ayahku bukan orang biasa.
Aku membaca beberapa potongan kliping koran yang bercampur dengan dokumen pribadi ayahku, aku membaca pemberitaan mengenai orang tuaku. Tentang hilangnya dua tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan. Mereka. Mereka mengasingkan diri ke tengah hutan segera setelah peristiwa gestapo terjadi. Dua tahun setelahnya, aku lahir. Bahkan ketika itu aku bisa mengerti, mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikerjakan ayah? Ibu seperti apa yang melahirkanku dari rahimnya? Mereka melakukan…. Hal-hal yang, aku tak tahu apa dasarnya.
Segalanya seolah benar-benar menjadi mimpi ketika pria itu berkata, “Kami rasa kamu tidak akan punya pilihan lain, selain ikut bersama kami.”
Mulailah aku didandani selayaknya perempuan pada umumnya. Gaun berpita, sepatu balet warna hitam, dan kalung mutiara. Rambutku yang biasanya kugelung lantas disisir dan diikat pita. Aku dibedaki dan bibirku diberi gincu, pipiku merona merah akibat sapuan pewarna pipi, dan alisku dibentuk.
Setiap hari aku mendapatkan materi tambahan di rumah. Diajari cara memanah, bertata krama, dan ekonomi serta politik negara. Terkadang, aku juga bermain-main dengan tabung dan botol-botol berisi zat kimia. Sesuatu yang orang-orang pikir pastilah dapat saja menurun dari kedua orang tuaku. Baru kutahu, kedua orang tuaku adalah Kimiawan. Senyatanya, hingga berminggu-minggu setelah mereka memberikan pendidikan itu padaku, aku tetap tak menunjukkan bakat apa pun.
Selain pendidikan yang diberikan di rumah, aku tidak lagi bersekolah di HIS, di mana para bumiputera biasa duduk belajar bersama keturunan Belanda, kali ini aku pergi ke ELS, tempat di mana peranakan Cina sepertiku, menurut keluargaku—aku tak lagi asing terhadap mereka, patut pergi menapasi ilmu. Di depan cermin kuamini pernyataan mereka, kulitku memang kuning langsat dan mataku sipit, baru kusadari setelah aku tinggal bersama mereka.***
Cerpen berjudul Sesuatu Telah Pecah di Senja Itu
Sesuatu Telah Pecah di Senja Itu
Mendadak semuanya menjadi begitu penting. Caranya menyingkirkan dengan sabar duri-duri ikan di piringku, suaranya ketika melantunkan doa, wajahnya ketika diam memikirkan sesuatu. Ah, ia selalu seperti itu. Sama dalam hal berpikir atau marah: diam. Dengan arah mata ke bawah tertuju pada pucuk hidungnya dan kedua tangannya bertemu di mulut, seperti tengah membungkam suara. Suatu saat ketika aku tanya mengapa, jawabnya, “Keduanya sama, jangan tergesa-gesa supaya tidak ada yang terluka.”
Mendadak semuanya menjadi tidak sederhana. Ia menyetrika sendiri pakaiannya, ia juga sering memasak makanan untuk kami: dirinya, aku, dan Ratri, anak kami yang masih bayi. Seingatku, ia tidak pernah marah dan bahkan bersuara keras padaku. Ia selalu bisa menunda, dan membicarakannya dengan nada sareh di lain waktu. Suatu saat ketika aku tanya mengapa, jawabnya, “Kanjeng Nabi tidak pernah bersuara keras pada istrinya.”
Aku bisa mengingat dengan jelas bahkan, ketika kami berdua baru melangsungkan pernikahan yang sederhana, waktu itu aku sedang haid. Sambil menunggu aku selesai dari rutinitas perempuan itu, ia menemaniku dengan cara mutih, hanya makan nasi dan minum air putih. Hingga tiba saat kami melakukan hubungan saresmi, laku seksual suami-istri, ia mengajakku menundukkan kepala, berdoa. Ketika aku sudah mulai menampakkan tanda-tanda kehamilan, semenjak itu ia melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, sampai Ratri lahir. Hampir sembilan bulan ia melakukannya. Saat aku tanya mengapa, jawabnya, “Hanya ini yang bisa kulakukan sebagai seorang calon bapak.”
Tapi tidak tepat benar kalimat itu. Ketika aku nyidham, aku menginginkan ikan kali hasil pancingannya. Waktu itu, malam menjelang pagi, ia dengan semangat berangkat berbekal senter, golok, dan garan pancing. Pagi ketika aku bangun, ia sudah ada di dapur memasak ikan hasil pancingannya, menghidangkannya untukku, dan sebagaimana biasa, menyisihkan duri-duri ikan di piringku agar aku tidak kesulitan memakannya. Ketika kandunganku mulai membesar, ia sering mengusap kandunganku sambil nembang lagu-lagu tentang kebajikan. Ketika aku tanya mengapa, jawabnya, “Ia sudah bernyawa dan bisa merasa.”
Dan aku tidak akan melupakan peristiwa yang ini. Waktu itu kandunganku sudah sangat tua. Soekarno datang ke daerah kami untuk kembali meneguhkan perlunya mengganyang Malaysia. Aku dan suamiku yang merasa sebagai anak kandung revolusi datang juga. Sebagai seorang aktivis politik yang disegani di wilayahku, seharusnya suamiku ada di jajaran kursi depan. Tapi ia menolak. Kalau tidak karena aku hamil tua, tentu ia sudah memilih untuk berdiri di tanah lapang bersama ribuan orang yang lain. Akhirnya kami duduk di kursi deretan belakang. Ketika acara bubar, dan kami hendak beranjak pulang, seseorang menghampiri suamiku, ia bertanya mengapa aku dan suamiku tidak meminta nama untuk calon bayiku pada Bung Karno? Dengan pandangan mata berbinar ke arahku, suamiku menjawab, “Istriku yang lebih berhak memberi nama anak kami. Ia yang merasakan penderitaan orang mengandung.”
Aku memberi nama anakku Wangi Ratri. Malam di saat aku melahirkan, dalam impitan pedih, dalam samar-samar wajah suamiku yang mencoba ikut menguatkanku, aku mencium bau wangi. Sangat wangi.
Aku hanya punya satu malam dalam hidupku. Malam penuh hujan di akhir tahun. Suamiku, dengan linang air mata, memeluk erat. Ia tidak mampu mengatakan sepatah kata pun. Tapi gigil tubuhnya dan kabar-kabar di luar memberiku isyarat kuat. Hujan turun di malam kepergian suamiku. Dengan masih membopong Ratri aku menutup pintu. Hujan turun menderas di dadaku. Tapi tidak di mataku. Tidak akan kubiarkan air mataku jatuh di wajah bayiku. Aku tidak ingin menularkan kecengengan pada kuncup kehidupan.
Semenjak kepergian suamiku, hari-hariku adalah hari-hari penuh waswas dan ketakutan. Di mana-mana aku mendengar kabar dan desas-desus yang membuat merinding. Rumah-rumah dibakar, penculikan, pembunuhan yang dilakukan ramai-ramai. Pada pagi buta kuputuskan pergi pulang ke rumah orangtuaku. Di sana kekhawatiran bukannya mereda. Semakin banyak orang yang mati dan semakin banyak kudengar nama-nama orang yang kukenal mati. Aku masih menahan semuanya, dan berharap tidak mendengar nama suamiku disebut dalam kabar-kabar buruk itu.
Hingga kemudian di pagi buta, aku dibangunkan oleh bapakku. Dengan segera kubopong Ratri menuju ruang tamu. Aku berpikir, kalaupun toh aku harus mati, aku ingin mati di depan bayiku. Kalaupun toh aku harus ’diambil’, aku ingin anakku bisa menyaksikan dengan mata timurnya, aku, ibunya, tidak pergi dengan tetesan air mata.
Di ruang tengah aku hanya melihat ibuku, pamanku, dan seseorang yang datang adalah Pono, teman dekat suamiku. Di depanku dan di depan orangtuaku, dengan suara pelan, Pono mengatakan pesan suamiku. Melalui Pono, dapat kutangkap dengan gamblang pesan itu. Suamiku berpesan supaya aku tidak berharap ia pulang, dan ia meminta agar aku bisa menyelamatkan hidupku dan hidup anakku. Suamiku bahkan menyarankan agar aku menikah kembali dengan seorang sahabatnya untuk bertahan dari situasi yang sangat sulit. Sebelum Pono pergi, aku masih sempat menghentikan langkahnya di depan pintu, aku menanyakan kejujurannya tentang nasib suamiku, apakah ia tidak akan selamat? Pono menggeleng kemudian bergegas pergi, menghilang. Aku merasa hidupku ambruk saat itu, tapi air mataku tidak jatuh.
Aku dan suamiku adalah orang biasa. Bagian dari masyarakat yang saat itu dibakar oleh semangat revolusi yang belum selesai. Suamiku hanya seorang guru yang sederhana dan dikenal baik oleh masyarakat. Ia berteman dan bersahabat dengan banyak orang yang bahkan berbeda pemikiran. Rumah kami, hampir tiap malam, menjadi tempat pertemuan baik untuk kepentingan organisasi yang diikuti oleh suamiku, maupun untuk pertemuan dengan teman-temannya yang lain. Di rumah kami yang sederhana, sering datang seorang mantri suntik yang sangat baik dan seorang seniman yang juga sangat baik serta halus budi bahasanya. Mereka berdua adalah orang-orang yang satu organisasi dengan suamiku. Pak Mawardi, mantri suntik itu, kudengar mati dibakar massa di rumahnya, rumah yang sering dipakai untuk menolong orang sakit tanpa pamrih. Sedangkan Sunardi, seniman yang pintar menari, yang wajahnya sangat ayu dengan kebaikan dan kehalusan hatinya, konon ditemukan tanpa kepala di sebuah parit tidak jauh dari rumah kami dulu.
Aku sungguh tidak tahu mengapa ada pembunuhan demi pembunuhan. Ketakutan ada di mana-mana. Semua orang seperti punya taring, semua udara seperti bertelinga. Banyak orang hilang tanpa sebab. Desas-desus terus membadai. Malam-malam semakin terasa mengeras. Aku mulai mendengar desas-desus tentang kematian banyak perempuan. Aku mulai mendengar banyak perempuan yang diambil menyusul suaminya. Cerita-cerita itu, duh….juga dilengkapi dengan perlakuan-perlakuan keji. Bu Marni boleh mengirim makanan untuk suaminya setelah ’digilir’ para petugas. Seminggu kemudian suaminya mati karena kelaparan dan siksaan di penjara. Mbak Rukmi menjual semua hartanya untuk ’membayar’ agar suaminya keluar. Uang diterima petugas. Beberapa hari kemudian, ia baru tahu suaminya sudah lenyap dari penjara itu.
Aku semakin waswas dengan keadaan diriku, terutama Ratri. Di masa-masa seperti itu, nyawa begitu tidak berguna. Kehidupan sudah bukan lagi sesuatu yang patut dihormati dan dihayati. Setiap orang bisa hilang dan mati kapan saja. Ia bisa mati hanya karena pernah datang di suatu rapat. Ia bisa mati hanya karena pernah bergaul dengan orang yang dianggap berbahaya. Ia bahkan bisa mati hanya karena sebuah suara dan telunjuk yang secara ngawur diarahkan padanya, entah dari sudut gelap yang mana. Berbulan-bulan aku menanggungnya. Pada malam-malam itu aku selalu menunggu dan berharap semoga malam itu bukan malam terakhirku.
Hingga kemudian Rahmat datang. Ia datang dengan wajah serba salah dan masygul. Rahmat adalah sahabat suamiku dan sahabat Pono. Mereka bertiga berbeda organisasi politik, tetapi menjalin persahabatan dengan baik. Rahmat anak seorang kiai yang cukup ternama di kecamatan lain. Orangtuanya adalah kenalan baik suamiku dan teman baik bapakku.
Dengan ditemani kedua orangtuaku, aku menemui Rahmat. Dengan suara pelan, Rahmat menceritakan pertemuannya dengan Pono beberapa bulan yang lalu. Pono membawa amanat dari mendiang suamiku agar Rahmat bersedia menikahiku. “Saya tidak tahu harus bagaimana Mbakyu. Tapi apa pun keputusan Mbakyu, saya manut.” Dan aku melihat air mata Rahmat menggenangi kedua matanya. Mata sahabat suamiku yang santun dan saleh.
Sebelum itu semua terjadi, aku sudah memikirkannya. Mencoba memikirkan dengan jernih. Situasi tidak kunjung membaik. Aku hidup tanpa suami dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Aku butuh suatu pegangan, setidaknya lepas dari impitan ketakutan, rasa waswas, dan nasib yang tidak menentu. Aku juga memikirkan Ratri.
Tetapi ketika aku hendak memutuskan, semuanya kembali sebagai sesuatu yang sangat sulit. Duh, Gusti, mengapa pisau uji-Mu begitu landhep, begitu tajam memangkas dan memotong seluruh kehidupanku. “Wuk Cah Ayu, kadang kala banyak jalan hidup yang tidak bisa kita pahami. Hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih. Ini bukan masalah senang dan tidak senang. Tapi putuskanlah. Sebab hidup ini adalah sebuah keputusan. Juga mungkin yang berhubungan dengan katresnan. Kamu tidak sedang berhadapan dengan kehidupan yang sewajarnya. Kamu berhadapan dengan dunia binatang.” Bapakku dengan suara groyok, seperti menahan tangis, mencoba memberi saran.
Aku mengangguk. Demi hidup ini sendiri. Demi Ratri.
Tahun-tahun awal pernikahanku dengan Rahmat adalah tahun-tahun yang paling sulit kupahami. Semua serba canggung, di antara segala pernik kehidupan sehari-hari, dan kesedihan yang sering menyelinap berkali-kali. Seluruh hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa tiba-tiba menjadi penting. Satu kejadian kecil tiba-tiba seperti membuka kotak ingatanku. Langkah kaki, suara orang bercakap-cakap, derit pintu, terutama jika hujan turun.
Bertahun-tahun aku hanya bisa diam dengan hati yang sering teriris hanya karena ada ikan kali di meja makan. Rahmat bertindak dengan bijak, ia tidak pernah mengail ikan dan tidak pernah makan ikan kali. Bertahun-tahun aku tidak bisa menyangkal suara-suara yang keluar dari mulut Ratri, suara anak kecil yang renyah tiba-tiba bisa menggaungkan banyak kalimat yang diucapkan oleh bekas suamiku. Dan bertahun-tahun itu pula, Rahmat tidak pernah menagih untuk melakukan hubungan suami-istri. Ia sabar, banyak melayaniku, dan mungkin jauh di perasaannya, aku tetap istri sahabat yang dihormatinya.
Berkali-kali pula aku meminta maaf pada Rahmat, mengaku berdosa sebab aku merasa sedang tidak berbuat adil. Tapi ia tetap dengan kesabarannya yang khas, merasa sangat mengerti apa yang aku rasakan. Menurutnya, lebih baik aku tidak berusaha melupakan semua itu. Aku harus menerimanya, menerima seluruh hal termasuk kenangan-kenangan yang sulit dilupakan. Sebab tanpa itu semua, aku tidak pernah sampai pada kehidupanku yang sekarang ini. Aku tumbuh bersama seluruh peristiwa dan kenangan. Semua itu sah sebagai bagian dalam hidupku.
Dan aku mencoba menerimanya. Menerima keadaanku, menyadari bahwa semua itu pernah kulalui, dan itu penting dalam hidupku. Aku mulai menerima bahwa mendiang suamiku sudah tidak ada lagi. Aku harus menjalani kehidupanku selanjutnya. Dan aku tak hendak membuang seluruh peristiwa bersama mendiang suamiku dari kenanganku. Tapi tentu aku tidak akan melupakan mengapa peristiwa sedih itu menimpaku. Aku tidak tahu dosa dan kesalahanku, aku tidak tahu dosa dan kesalahan mendiang suamiku. Seluruh peristiwa yang membuatnya pergi dariku tidak akan kulupakan dan tidak akan kumaafkan. Aku bukan memendam dendam, aku hanya tidak memaafkan.
Apa kesalahannya? Bukankah ia hanya seorang guru yang sederhana? Bukankah ia bermasyarakat dengan baik? Ia tidak pernah melakukan kejahatan. Ia bukan pencuri, bukan perampok. Hampir di seluruh hidupnya bahkan digunakan buat kebaikan dan memikirkan orang lain. Apa yang salah dari mendiang suamiku, juga Mantri Mawardi, dan Sunardi?
Setiap kali rasa marah itu memuncak, Rahmat selalu berusaha menenangkanku. Ia mencoba menuntunku untuk berdamai dengan masa lalu. “Percaya saja hukuman itu akan datang, entah kapan dan datang dari mana. Tapi kalau kamu tidak mencoba berdamai dengan masa lalumu, kamu akan rugi. Semua itu hanya akan membuat mereka terus berteriak menyoraki kehidupanmu. Untuk yang seperti itu, aku tidak akan merelakannya.” Sambil berkata seperti itu, Rahmat menatap tajam pada mataku. Saat itu. Untuk kali pertama, aku memeluknya, erat. Sangat erat.
Pada akhirnya, aku bisa menerima itu semua. Bukan hanya tentang mendiang suamiku. Tapi aku menerima Rahmat sebagai seseorang yang kupunyai dan kucintai. Jika hidup itu sendiri adalah sebuah keputusan: diterima atau tidak, dilanjukan atau diakhiri. Cinta tidak lebih dari itu semua. Mencintai pada akhirnya adalah sebuah keputusan. Dan karena sebuah keputusan, maka berbagai pertimbangan sah menjadi landasannya. Pada akhirnya, toh cinta, sebagaimana banyak hal yang lain: tidak turun dari langit yang gaib. Ia, cinta, hanya bisa diputuskan dan dikerjakan.
Anak keduaku lahir. Seorang perempuan cantik, namanya Laila. Ia juga lahir di malam hari. Kelahirannya membuatku semakin yakin dengan jalan hidup yang kutempuh. Kini ada semakin banyak anak-anak harapan yang bisa kukerjakan. Kami bahagia.
Lalu datang senja itu. Beberapa hari sebelumnya, aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Aku sering merasa tiba-tiba ada yang mengagetkanku. Aku merasa tiba-tiba ada mendiang suamiku di dekatku. Aku merasa tiba-tiba sering kosong, mengerjakan sesuatu tanpa kesadaran.
Hingga benar-benar datang senja itu. Awalnya, Laila yang baru saja pulang dari sekolah sore, memanggilku di dapur, katanya ada tamu. Aku bergegas ke depan, tapi aku tidak mendapati apa-apa. Laila juga bingung. Aku nratab, deg-degan tak karuan, entah kenapa. Lalu aku kembali masuk ke dalam, mencoba mempersiapkan masakan di meja makan dengan perasaan tidak menentu. Laila lalu masuk lagi ke dapur untuk mengabarkan bahwa ada tamu, tamu yang tadi. Dengan cepat aku keluar. Kali ini, aku benar-benar kaget.
Duh Gusti, Pono! Ia berdiri mematung di depan pintu. Sejenak menatapku, lalu menundukkan kepala. Aku segera menggandengnya untuk masuk ke dalam. Aku membuatkannya teh hangat, tapi perasaanku semakin tidak karuan. Sehabis mempersilakannya minum, pandangku kembali terhenti di depan sosok yang sudah belasan tahun tidak hadir dalam hidupku. Ia jauh lebih tua dari usia seharusnya. Tapi aku memakluminya. Hidup yang kejam tentu telah dilaluinya. Ia lebih banyak diam. Setiap kali aku bertanya tentang kabarnya, ia hanya menjawab singkat dengan kata-kata yang tidak jelas. Dan aku mencoba memakluminya. Hidup yang kejam membuatnya tidak gampang mengeluarkan kata-kata. Ia lebih banyak melihat ruang tamu, perkakas yang ada di sana, potret-potret di dinding. Ia seperti ingin menanyakan sesuatu, aku menangkapnya sebagai pertanyaan terhadap Laila. “Ia anak keduaku dengan Rahmat. Namanya Laila. Ratri, kakak Laila, sedang pergi dengan suamiku ke rumah neneknya. Tapi ia pasti pulang malam ini. Kamu harus menunggu mereka.”
Pono diam. Tiba-tiba ia menggeleng cepat. “Tidak, aku harus cepat pulang.”
Aku agak terkejut dengan jawabannya. Aku merasa ada sesuatu yang hendak dikatakan padaku. Jangan-jangan…..Ah, tapi tidak. Mendiang suamiku sudah pergi. Semoga arwahnya tenang di sisi Gusti Allah.
Pono bangkit. Dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa mengantarnya sampai pintu. Beberapa langkah dari pintu, Pono kembali menengok. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian tetap urung. Ia kembali melangkah pergi. Tanpa kata-kata. Ketika sampai di luar pagar rumah, Pono kembali menengok ke belakang, ke arahku. Benar. Aku sangat yakin ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Agak lama ia terdiam. Dan ia benar-benar melangkah pergi. Senja membuatnya menjadi bayang-bayang, mengabur, lalu lenyap.
Sebuah kepastian menyergapku kuat. Mendiang suamiku belum meninggal dunia! Dalam ragu, dan rasa tak tentu, aku melangkah keluar pintu rumah. Sampai di pelataran rumah, aku terhenti. Ada sesuatu yang membuatku berhenti mengejar Pono. Aku seperti berada pada satu perbatasan. Batas yang sangat rumit. Dadaku sesak. Senja menggelap di pelataran. Aku terguncang. Tangisku pecah di pelataran. ***
Cerpen berjudul Ripin
KETIKA kawan-kawannya berhamburan ke jalan raya, Ripin sedang susah payah menghitung jumlah kelereng yang dimenangkannya. Siang itu tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa masa kecilnya akan segera berakhir. Dua puluh dua, mungkin lebih. Ia cepat-cepat memasukkan kelereng-kelereng itu ke dalam saku celananya dan bergegas menyusul kawanannya.
Penarik perhatian kawanan itu tak lain adalah mobil pick up berpengeras suara dan digantungi poster besar berwarna-warni. Mesin mobil itu bergerung seperti tak mau kalah ribut dengan pengeras suara, membuat lagu Rhoma Irama terdengar lebih buruk dari yang biasanya Ripin dengar dari radio Bapak. Ketika mobil itu melintas di depan mereka, Ripin dikejutkan tatapan laki-laki di sebelah sopir yang sedang memegang mikrofon. Laki-laki itu punya cambang dan janggut yang rapi seperti Rhoma Irama. Rambut keritingnya pun seperti Rhoma Irama. Ripin sempat teringat bapaknya Dikin yang juga punya cambang, janggut, dan rambut seperti Rhoma Irama, tapi bapaknya Dikin sudah lama mati ditembak.
Entah siapa yang mulai, seluruh kawanan itu tiba-tiba saja sudah berteriak-teriak girang dan berlarian di belakang mobil. Berlari mengejar mobil yang lajunya tidak lebih cepat dari sapi, Darka, kawannya yang bertubuh paling besar, berhasil melompat naik ke bagian belakang mobil dan bertolak pinggang jumawa. Begitu beberapa yang lain mencoba mengikuti Darka dan terjatuh, sorak-sorai kawanan itu terdengar semakin riuh.
Ripin berlarian agak jauh di belakang. Duapuluhan kelereng yang dimenangkannya dan belasan yang lain yang merupakan modalnya, membuat kantung celananya sesak, dan kejadian semacam ini bukannya tak pernah ia alami. Dulu, jahitan di celananya sobek dan kelerengnya berhamburan. Kawan-kawannya berebutan mengambil kelereng-kelereng itu dan tak seorang pun bersedia mengembalikannya. Kali ini ia harus hati-hati.
Semula, Ripin berencana untuk mengikuti kemanapun kawanannya berlari, tapi pengumuman yang didengarnya dari pengeras suara itu membuatnya berhenti. Di antara suara musik ketipung dan mesin mobil, lamat-lamat didengarnya suara, seperti suara Rhoma Irama, sedang mengumumkan pasar malam, tong setan, dan rumah hantu. Nanti malam, di alun-alun. Ripin tercenung, lalu berbalik arah dan berlari pulang ke rumah.
Mak sedang duduk meniup tungku ketika Ripin menerobos masuk ke dapur sambil terengah-engah. Tak bisa ditangkapnya dengan jelas apa yang dikatakan mulut kecil anaknya. Ripin sibuk berceloteh sembari memasukkan kelereng-kelerengnya ke dalam sebuah kaleng bekas susu. Suaranya bertumpuk-tumpuk dengan bunyi kelereng yang satu per satu membentur dinding dalam kaleng. Hanya sepotong-sepotong dari kalimat Ripin yang bisa didengar Mak, tapi itu cukup. Tak ada pasar malam. Tak ada tong setan.
Ripin merajuk. Mengatakan setengah berteriak tentang kedatangan Rhoma Irama dan berharap Mak terbujuk. Mak berpikir, bagaimana mungkin Rhoma Irama mau datang ke kota busuk ini. Rhoma Irama cuma mau datang ke Cirebon atau Semarang. Tegal mungkin saja, tapi tidak kota kami. Begitupun, nama ini membuat raut muka Mak sempat berubah cerah sebelum kemudian keningnya berkerut cemas.
Ripin tahu itu. Ripin tahu kalau Mak diam-diam menangis setiap kali mendengar Rhoma bernyanyi di radio. Ripin bahkan pernah melihat Mak mendekap dan menimang-nimang radio itu. Padahal Mak sudah bersumpah tidak menangis. Sekeras apapun Bapak menghantam wajah Mak.
Ripin melihat cemas ke wajah Mak dan berharap sekali ini Mak masih mau berbuat nekat. Harapan ini malah membuat Ripin merasa berdosa. Terakhir kali Mak nekat, pulang nonton layer tancap Satria Bergitar, Bapak menghajar Mak sampai dini hari. Kalau sudah begini Ripin cuma bisa nyumput dibawah selimut dan menahan mulutnya yang menangis supaya tidak bersuara.
“Mak beli duwe duit,” kata Mak berbohong. Ripin tahu Mak menyimpan sedikit uang di kaleng biskuit tempat bumbu dapur. Cukup buat ongkos dan beli es lilin. Ripin marah karena Mak berbohong. Kemarahan membuatnya tidak lagi peduli pada ingatan atas bilur-bilur di wajah Mak. Mak, bohong itu dosa.
Sekali lagi Ripin menyebut nama Rhoma Irama, bersumpah demi Allah bahwa ia sudah melihatnya. Ganteng benar.
“Ganteng kien karo bapane Dikin.”
Mak tercenung. Ripin mengeluarkan semua senjatanya. Dia tahu, Mak senang dengan bapaknya Dikin. Kalau bapaknya Dikin lewat depan rumah, Mak suka mengintip dari belakang pintu. Suatu kali bahkan ia pernah melihat bapaknya Dikin sembunyi-sembunyi keluar dari pintu dapur rumahnya dan semakin bergegas begitu bersitatap dengan Ripin. Hari itu Mak kasih duit jajan, Ripin malah tambah curiga. Tapi Ripin tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun.
Raut wajah Mak mengeras. Mak pasti berpikir tentang Bapak. Mak takut. Ripin sempat berpikir untuk pergi sendiri ke pasar malam. Sepertinya itu tidak sulit. Semua orang pasti tahu dimana tempat pasar malam didirikan, ia tinggal tak perlu malu-malu bertanya. Sayangnya ia masih takut. Nenek dulu pernah pesan agar Ripin tidak membantah Mak atau Bapak. Jangan main kemalaman. Hukuman untuk anak durhaka adalah kehilangan jalan ke rumahnya dan dikutuk untuk tersesat selamanya, begitu kata Nenek. Ripin bergidik dan semakin cemas kalau Mak menolak ajakannya.
Dulu Mak dan Ripin bisa bersenang-senang setiap malam, karena Bapak bisa dipastikan belum pulang sebelum Subuh. Bapak tidur sepanjang siang, dan kelayapan sepanjang malam. Memang Mak belum sempat mengajaknya ke kota, tapi setidaknya mereka tidak pernah lewat tontonan apapun yang ada di kampung mereka. Mak bahkan menemaninya nonton TVRI di kelurahan.
Itu dulu, waktu Bapak masih jagoan yang paling hebat. Sekarang sudah ada jagoan yang lebih hebat dari Bapak. Kata orang-orang, jagoan ini seperti setan. Tidak ada yang tahu siapa orangnya, dimana rumahnya, seperti apa tampangnya. Bapaknya Dikin salah satu korbannya. Suatu pagi ditemukan mayatnya mengambang di kali, luka tembak dua kali, di dada dan di dahi. Jagoan-jagoan setempat banyak yang sudah duluan mati. Dari namanya, Ripin menduga jagoan ini pastilah orang Kresten.
Semenjak jagoan setan ini berkeliaran, Bapak sering pulang. Bahkan bisa berhari-hari tidak keluar rumah. Mak dan Ripin jadi tidak bisa lihat tontonan dan Bapak jadi lebih sering menghajar Mak. Semenjak itu pula Bapak memutuskan untuk mengajar Ripin mengaji. Bosan menghajar Mak, diajar Bapak mengaji buat Ripin sama dengan bersiap-siap di hajar rotan.
Baru seminggu terakhir ini, Bapak rupanya sudah tidak tahan berdiam di rumah berlama-lama. Ia mulai sering keluar malam, tapi jadwalnya semakin sulit dipastikan. Tidak ada yang tahu untuk berapa lama ia pergi dan kapan ia pulang.
Sampai sore, Mak kelihatan gelisah, mondar-mandir di dapur. Ripin tahu kalau Mak gelisah artinya Mak sudah tidak tahan untuk dolan dan bersenang-senang. Mak sudah bosan dengar radio. Kalau sudah begini, Ripin tidak akan mendesak Mak lagi. Keputusannya sudah hampir bisa dipastikan, Ripin tinggal menunggu Mak menemukan jalan keluar. Sampai sore pula, Ripin ketiduran di kursi depan. Mimpi naik komidi putar.
Bapak masuk dan menendang kursi yang diduduki Ripin. Ripin terkejut, terjaga dan mendapati tangan kekar Bapak memuntir daun telinga kanannya. Dengan kasar, Bapak menyeretnya ke arah sumur, dan perintah Bapak kemudian tidak perlu dikatakan lagi. Ripin mengambil air wudhu dan bergegas shalat ashar.
Sehabis shalat, Bapak sudah menunggu di meja makan. Rotan panjang disiapkan di sisi kirinya dan Ripin mengeja huruf Arab di depannya dengan terbata-bata. Bapak sepertinya mabuk. Dari mulutnya keluar bau asam yang menusuk-nusuk hidung Ripin. Kalau mabuk, biasanya pukulan rotannya lebih keras. Belum dipukul Ripin sudah merasa tubuhnya nyeri.
Baru 10 ayat, Ripin melihat Bapak sudah menempelkan kepalanya ke meja. Di ayat ke-12, Ripin ragu-ragu bahwa yang didengarnya adalah dengkur halus Bapak. Di ayat ke-16 Ripin berhenti, Bapak sudah benar-benar tertidur. Dengkurnya keras sekali.
Ripin tak bisa memutuskan apakah sebaiknya ia pergi. Ripin tak bisa membayangkan kemarahan macam apa yang akan menimpanya jika Bapak tiba-tiba terjaga dan ia tak ada dihadapan Bapak. Pasrah, ia duduk dihadapan Bapak, dalam diam. Ia pikir, meneruskan mengaji pastilah percuma. Lebih baik diam. Sial, tiba-tiba Ripin kepingin kencing. Mak masih mondar-mandir di dapur. Ripin duduk tegang dan yang terlintas di kepalanya adalah wahana rumah hantu di pasar malam.
Menjelang maghrib barulah Bapak terjaga. Ripin masih duduk diam, menahan kencingnya, di depan Bapak. Keadaan menahan kencing membuat Ripin tidak terlalu siaga. Terjaga dan mendapati Ripin sedang mematung, membuat rotan di sisi kiri Bapak melayang ke arah tangan kanannya dengan keras. Ripin tersentak dan langsung memasang wajah pucat, tidak sepenuhnya karena perasaan sakit ditangannya. Ripin kencing.
Bapak mendengar bunyi gemericik itu dengan tatapan terpana. Ia melihat ke bawah meja lalu berdiri tegak menyambarkan rotan di tangannya ke wajah Ripin, sembari dari mulutnya tersembur sumpah serapah. Ripin menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan Bapak terus memukulinya. Ripin tak bisa menahan diri untuk tidak menangis dan menjerit kesakitan. Dalam kesakitannya ia merasa menonton Tong Setan jadi semakin tidak mungkin, sehingga ia menjerit lebih keras lagi. Mak bergegas datang dari arah dapur, memegangi tangan Bapak dan memohon padanya untuk menghentikan perbuatannya.
Bapak memang berhenti memukuli Ripin, tapi hasrat memukulnya sudah terlanjur tinggi. Bapak menyabetkan rotannya beberapa kali ke tubuh Mak. Mak terduduk di lantai, dan bergerak mundur hingga punggungnya menyentuh dinding, dan Bapak belum selesai. Mak tidak menjerit atau menangis. Mak diam. Tubuhnya seperti patung. Ripin berpikir bahwa kejadiannya akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Mak akan menutupi wajahnya, dan Bapak akan berhenti karena kelelahan.
Sore itu, ternyata tidak sama. Ripin tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah beberapa lama sabetan rotan itu mengenai tubuhnya, Mak tiba-tiba mendongak, lalu menatap Bapak lekat-lekat. Ripin tahu apa artinya tatapan itu. Tatapan itu pernah ia tujukan pada Darka, sesaat sebelum perkelahian mereka dulu. Sebelumnya Ripin takut pada Darka, tapi saat ia menatap tajam-tajam itu, ia sudah tidak akan takut lagi. Mak sudah tidak takut lagi.
Hampir bersamaan, terdengar azan maghrib dari surau. Entah mana, azan maghrib atau tatapan Mak yang menghentikan Bapak. Bapak menoleh ke arah Ripin dan mengancam akan memukul Ripin lagi jika saat shalat nanti Ripin tak ada di surau. Bapak mengambil sarungnya dan berlalu membanting pintu.
Ripin tiba-tiba melihat Mak mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bangkit dengan sigap, lalu bertanya padanya, “Sira arep melu Mak apa Bapak?” Ripin menyebut, “Mak,” dengan gemetar. Mak masuk ke kamar, lalu tergesa-gesa memasukkan pakaian-pakaiannya dan Ripin ke dalam tas. Di depan lemari Mak sempat berhenti dan berpikir apa lagi yang perlu dibawanya. Tak jelas alasan Mak memasukkan kotak berisi perhiasan imitasi yang tidak ada harganya ke dalam tas itu.
Sebentar kemudian Mak sudah menggandeng tangan Ripin menyusuri jalan yang semakin gelap ke arah kota. Mak berjalan dengan langkah-langkah cepat dan lebar, dan Ripin kepayahan mengimbanginya. Tidak ada sepatah katapun diucapkan Mak dan Ripin melangkah dengan penuh perasaan takut. Jalan raya sudah dekat, kurang dari seratus meter. Tiba-tiba Mak berhenti. Terlihat berpikir keras, lalu berbalik arah. Setengah bergumam Mak bilang bahwa dia lupa bawa uang. Tergesa-gesa, Mak menyuruh Ripin menunggu. Tidak menunggu jawaban, Mak berlari ke arah rumah, meninggalkan Ripin sendirian.
Mulanya Ripin berdiri di jalan kampung yang lengang itu dan bermaksud menuruti Mak, namun kemudian kecemasan bergumul dan meningkat cepat. Ripin memutuskan berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah. Tas besar yang dibawa Mak ditinggalkannya tergolek di atas jalan.
Terengah-engah, di depan rumahnya, ia mendapati pintu depan terbuka dan di dalam ruang tengah, ia dapat melihat Bapak sedang menjambak rambut Mak dan sedang menghantamkan kepala Mak yang kecil itu ke arah dinding.
Pintu masuk Tong Setan sudah dibuka. Orang-orang berebut membeli karcis. Ripin melangkah masuk dengan perasaan takjub. Orang-orang berebut menaiki tangga yang berdiri di samping tong yang sangat besar, dan Sam terdorong-dorong. Di bagian atas, Sam meniru beberapa anak yang menaiki undakan yang rupanya disediakan untuk anak-anak seukurannya. Orang-orang berebut melongok ke dalam tong.
Tong itu, Ripin teringat sumur di belakang rumahnya. Di dalam tong itu dua orang sudah mulai menjalankan trail. Lalu perlahan, seperti sihir, kedua motor itu mulai merambat di dinding tong dan semakin lama berputar semakin cepat. Ripin terkesima dengan apa yang dilihatnya sekaligus menyesal. Seandainya Mak bisa ikut. Ripin terus melihat ke arah kedua motor yang kemudian saling melompat-lompat satu sama lain. Ripin semakin terkesima begitu kedua motor itu menyusuri dinding tong sampai hampir sampai di ujungnya, begitu dekat dengan tempatnya berdiri. Tangan kecilnya bisa meraih motor-motor itu.
Tong Setan berakhir. Ripin ingin bertahan sebentar di sana, untuk menyaksikan lebih banyak lagi, tapi petugas tiket menemukannya dan mengusirnya pergi. Di luar, sebenarnya ada banyak yang belum disaksikan Ripin. Dia belum naik Komidi Putar, belum masuk Rumah Hantu, tapi tak ada uang sepeserpun tersisa dikantungnya. Kaleng tempat Mak menyimpan uang sudah dibuangnya dari tadi. Kaleng yang sekarang di genggamnya hanya berisi kelereng. Tidak ada yang mau menukar karcis masuk dengan kelereng.
Di luar, kompleks pasar malam begitu ramai. Kemanapun Ripin melangkah ia hanya melihat kegembiraan. Mak tentu akan senang, jika bisa ada di sini. Begitu ia ingat Mak, ia ingat Rhoma Irama yang mengumumkan pasar malam dengan mobil siang tadi.
Ripin mengikuti firasatnya untuk mencari arah sumber pengeras suara. Benar. Di depan sebuah meja berisi berbagai jenis jenggot dan cambang palsu, si Rhoma Irama berdiri, tetap dengan mikrofon dan suaranya yang merdu. Ia memakai pakaian yang gemerlap, persis yang pernah dilihatnya di sebuah poster Rhoma Irama. Ripin mendekat untuk memastikan sekali lagi. Jika benar ini Rhoma Irama, ia akan bisa menceritakannya pada Mak, biar Mak ikut senang. Harusnya ia berusaha lebih keras membangunkan Mak, tapi Ripin tidak tega. Tidur Mak pulas sekali.
Ripin sudah begitu dekat, dirinya dan laki-laki berpakaian gemerlap itu hanya dipisahkan meja, tapi laki-laki tidak sedikitpun memicingkan mata pada Ripin. Ripin mencoba menarik perhatian laki-laki itu, tapi rupanya ia sedang sibuk dengan berbagai pengumumannya. Iseng, Ripin mengambil satu ikat cambang dan jenggot palsu lalu menyelipkannya ke dalam kantong celananya. Laki-laki berpakaian gemerlap itu tidak menggubrisnya.
Ripin memutuskan untuk berseru padanya. “Hey, Rhoma Irama!” teriaknya lantang. Orang-orang di sekitarnya menoleh dan tertawa tercekikik. Laki-laki berpakaian gemerlap itu terkejut, lalu menoleh ke arahnya. Sadar bahwa teriakan bocah ini telah membuat lebih banyak orang memperhatikannya, laki-laki, dengan mikrofon di depan mulutnya, berkata. “Bukan. Bukan Rhoma.” Laki-laki lalu mengubah posisi berdirinya, seperti sedang berjoget. “Namaku Ruslan. Ruslan Irama,” katanya dengan suara yang berat dan basah. Orang-orang tertawa.
Ripin menatapnya dengan pandangan kecewa. “Hey, Bocah,” tegur Ruslan Irama. Ripin mendongak, gagal menutupi matanya yang mulai berkaca-kaca.
Ripin menyebut namanya dengan gemetar dan malu.
“Ah, bagus sekali. Ripin. Ripin dari Arifin.”
Lalu Ruslan Irama tiba-tiba bersuara lantang. “Semua orang bisa menjadi seperti bang haji Rhoma Irama. Siapapun juga. Pengunjung pasar malam yang kami hormati, sambut calon artis besar kita, Arifin Irama,” kata Ruslan Irama. Orang-orang yang berkumpul di sekitar meja Ruslan Irama bertepuk tangan ke arah Ripin. Lalu Ruslan Irama mengambil gitarnya. “Mulanya adalah akhlak. Lalu musik.” Lalu Ruslan Irama memetik gitarnya. Belum pernah Ripin melihat gitar yang begitu indah. Berwarna hitam mengkilat, dengan motif dengan warna emas. Suaranya nyaring dan halus.
Gitar yang indah itu masih terkenang-kenang ketika pasar malam bubar dan lampu-lampu mulai dimatikan. Persis di depan jalan masuk pasar malam, barulah Ripin sadar ia tak tahu kemana pulang. Neneknya benar. Rumahnya hilang.
Kebingungan, Ripin malah kembali melangkah masuk ke dalam komplek pasar malam. Langkah kakinya membawanya ke dekat meja Ruslan Irama. Ia terkejut melihat tidak ada siapapun di sekitar meja itu. Hanya ada sebuah gitar hitam mengkilat, tidak ada Ruslan Irama. Dengan hati-hati ia menyentuh gitar itu, lalu mengangkatnya. Ia semakin terkejut melihat betapa gitar itu begitu ringan.
Beberapa puluh menit kemudian ia menyusuri trotoar yang entah menuju kemana. Ia menyandang gitar yang dicurinya dengan keberanian yang entah datang dari mana. Ia ingat Mak. Ia tersenyum. Satu-satunya yang tidak entah adalah bahwa Mak akan selalu mencintai Rhoma Irama. Itulah yang akan diraihnya. Ia akan menjadi Rhoma Irama, bukan sekadar Ripin Irama. Setiap kali Mak akan memeluk dan menimangnya.
Sampai puluhan tahun kemudian, satu kenyataan gelap yang luput dimengertinya adalah bahwa malam itu, setelah kepala Mak menghantam dinding, Mak mati. Kenyataan lain yang tidak diketahuinya: beberapa hari setelah kematian Mak, mayat Bapak ditemukan mengambang di kali, dengan lubang di dada dan di dahi, di tembak jagoan seram bernama Petrus.
Ripin tidak pernah kembali. ***
Baca Juga: Kumpulan Contoh Teks Tanggapan Singkat Beserta Strukturnya | Bahasa Indonesia Kelas 9